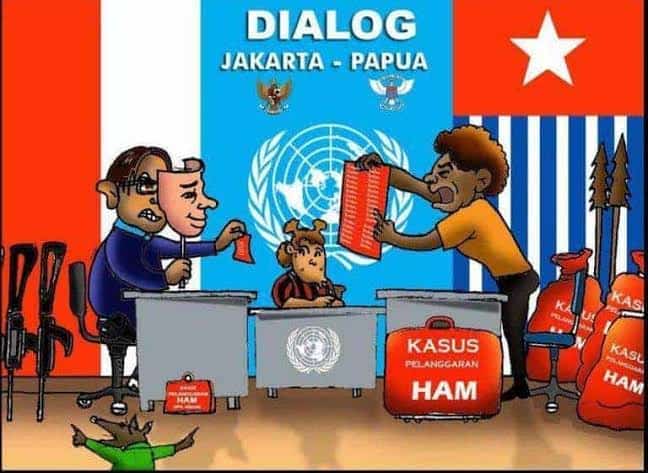Oleh: Alvina Septi Sekar Sari*
Aborsi merupakan sebuah tindakan secara sengaja, untuk mengakhiri kehamilan sebelum embrio atau janin mempunyai kemampuan hidup di luar rahim. Tindakan aborsi biasanya dapat dilakukan secara medis atau bedah. Namun, tentu saja isu ini menjadi perdebatan karena melibatkan pertanyaan seputar hak-hak perempuan, hak-hak reproduksi, agama, moralitas, dan kesehatan.
Beberapa negara mengizinkan aborsi sebagai hak kesehatan reproduksi perempuan, sementara negara lain melarang sepenuhnya atau dengan beberapa pengecualian. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, pilihan melakukan aborsi dipicu oleh situasi yang sulit, seperti kehamilan tidak diinginkan, masalah kesehatan, atau trauma fisik dan psikologis yang signifikan.
Saat ini, aborsi menjadi subjek yang kontroversial di berbagai negara, salah satunya ialah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak membebaskan masyarakatnya melakukan aborsi. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 75 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.
Akan tetapi, terdapat pengecualian bersyarat yang tertuang dalam ayat kedua yang berbunyi “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dalam kurun waktu 40 hari setelah haid pertama”.
Beban psikologis
Menurut saya, kebijakan yang tertuang dalam UU No.36 Pasal 75 ayat 1 dan 2 dan juga ditegaskan kembali pada UU Kesehatan pasal 31 Nomor 61 tahun 2014 mengenai diperbolehkannya melakukan aborsi yang dikarenakan kekerasan seksual dalam kurun waktu 40 hari setelah haid pertama, perlu dikritisi. Pelarangan dan pengecualian aborsi yang masih terbilang ketat merupakan bentuk opresi bagi kaum perempuan.
Menurut saya, pemerintah tidak memiliki pertimbangan kuat terhadap dampak yang mungkin timbul akibat dari kebijakan tersebut. Ilegalitas tersebut berdampak pada praktik aborsi tidak aman/ilegal yang berkontribusi pada biaya lainnya yang harus dipikul oleh perempuan. Biaya-biaya tersebut antara lain, ialah dampak psikologis dan trauma fisik yang dialami oleh perempuan, biaya sosial, termasuk pengucilan dan stigma negatif dari masyarakat, hilangnya pendapatan, dan biaya-biaya yang terkait dengan sistem perawatan kesehatan.
Paling tidak ada 2 poin yang ingin saya diskusikan. Pertama, terdapat beban dan trauma psikologis yang dihadapi perempuan ketika akhirnya memilih melakukan aborsi tidak aman/illegal, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Perempuan akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri, sedih berkepanjangan, trauma dengan sesuatu yang mengingatkannya akan kehamilan tak diinginkan serta keberadaan janinnya, stress berlarut-larut, merasa berdosa, menyesal, kecewa, dan cenderung hanya terpusat pada pandangan orang lain serta mengabaikan kesehatannya sendiri.
Adanya pelarangan aborsi bagi korban juga akan berdampak serius pada psikologis korban, karena kehamilan tersebut dapat menjadi pengingat terus-menerus tentang pengalaman traumatis yang mereka alami.
Pelarangan aborsi dalam kasus ini dapat memaksa korban kekerasan seksual untuk tetap hamil dan melahirkan anak dari pelaku kejahatan, yang dapat mengakibatkan tekanan emosional dan psikologis yang besar pada korban.
Selain itu, memaksa korban untuk melahirkan anak juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan emosional mereka, dan memperpanjang proses pemulihan dari trauma yang mereka alami. Ini juga bisa membatasi pilihan korban untuk mengontrol tubuh dan kehidupan mereka sendiri, yang bisa sangat merugikan bagi korban yang mungkin masih berusia muda atau tidak siap secara finansial maupun emosional untuk menjadi orang tua.
Kedua kebijakan tersebut telah melanggar hak dan kebebasan perempuan untuk memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Padahal, perempuan berhak penuh atas tubuh mereka sendiri dan bebas untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuhnya.
Kebebasan ini termasuk dalam menentukan keinginan untuk memiliki atau tidak memiliki anak, terutama dalam konteks kehamilan yang disebabkan karena kekerasan seksual atau pemerkosaan.
Padahal, angka pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia cukup tinggi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 21.093 perempuan menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2023. Tentu saja jumlah ini belum dapat menjadi acuan mutlak, karena hanya merujuk pada data kasus yang dilaporkan. Entah berapa banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terus terjadi namun tidak dilaporkan karena alasan ketakutan ataupun tekanan sosial lainnya.
Saya percaya bahwa status sosial seorang perempuan tidak seimbang dengan kaum laki-laki, terlebih apabila wanita tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Itu sebabnya pelarangan aborsi di Indonesia justru akan semakin mengopresi korban-korban kekerasan seksual karena sudah ada subordinasi terhadap perempuan itu sendiri.
The personal is political
Dengan refleksi ini, saya pun teringat dengan sebuah slogan aliran pemikiran Feminis Radikal berbunyi: ‘The personal is political’. Pada hakikatnya slogan ini bermakna bahwa pengalaman kesengsaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh seorang perempuan tidak dapat dianggap sebatas persoalan pribadi/personal. Ketidakadilan tersebut adalah persoalan politis karena berakar pada ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.
Pengalaman korban pelecehan dan kekerasan seksual seharusnya didengarkan dengan sensitivitas untuk keadilan. Hal itu termasuk memperhatikan hak-hak mereka terhadap aborsi jika mereka memilihnya. Pelarangan aborsi bagi korban pelecehan seksual dapat menambah penderitaan korban dan mengurangi pilihan yang seharusnya tersedia bagi mereka.
Apabila.masalah-masalah tersebut dikaji dan dicari kembali akar permasalahannya, adapun salah satu permasalahan ialah kurangnya perlindungan bagi perempuan dari kebijakan-kebijakan yang mengopresi. Tekanan aturan undang-undang dan dampak psikologis, fisik dan sosial yang besar terhadap perempuan membuat korban pelecehan seksual sendiri merupakan korban kekerasan struktural.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, khususnya para perempuan yang memiliki kekuasaan di eksekutif maupun legislatif mendorong payung regulasi yang mengurangi opresi terhadap perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual. Pemerintah baik laki-laki dan secara khusus perempuan yang memiliki privilege harus lebih banyak memberikan atensi pada peraturan perundang-undangan yang menindas dengan mendorong praktek jalur aborsi secara ilegal yang justru membahayakan tubuh, mental, psikologis dan bahkan nyawa korban.
Saya percaya bahwa awal dari jalan panjang menuju kebebasan perempuan dari kekerasan hanya dapat dicapai dengan merekognisi otonomi tubuh, identitas dan refleksi mereka, termasuk haknya untuk memilih apa yang baik untuk tubuhnya. (*)
* Penulis adalah anggota Komunitas SWARA Akar Papua (SWAP) dari Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua dan mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih (Uncen). Tulisan ini dibuat dalam rangka kampanye “16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP)” di Tanah Papua