Oleh: Digman Amelaman *)
Gereja hadir bukan pertama-tama sebagai lembaga yang menjelaskan kebijakan, melainkan sebagai ibu yang berjalan bersama umatnya. Di tanah Papua, di mana alam, budaya, dan iman tumbuh dalam satu nafas kehidupan, setiap keputusan yang menyentuh tanah dan masa depan masyarakat adat tidak pernah bersifat netral. Ia selalu menyentuh luka sejarah, harapan yang rapuh, dan martabat manusia yang sering kali terpinggirkan.
Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ mengingatkan kita bahwa krisis sosial dan krisis lingkungan bukanlah dua persoalan yang terpisah. Tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan relasi spiritual. Karena itu, pembangunan yang sejati tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau janji kesejahteraan, melainkan dari sejauh mana manusia, terutama yang paling kecil, tetap menjadi subjek, bukan korban, dari perubahan.
Dalam terang iman Katolik, kesejahteraan umum (bonum commune) tidak pernah dicapai dengan mengorbankan suara mereka yang lemah. Sebaliknya, kesejahteraan umum lahir dari keberanian untuk mendengarkan jeritan umat, menghormati kebijaksanaan lokal, dan memberi ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat secara penuh dan bermartabat dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Gereja dipanggil untuk berdiri di tengah, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pendamping yang setia dan kritis.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Refleksi pastoral ini mengajak kita untuk memaknai kembali peran Gereja dalam relasi dengan negara dan kekuatan ekonomi. Kerja sama demi kesejahteraan umat memang penting, namun kerja sama itu harus selalu dilandasi oleh kebebasan profetis Gereja. Gereja tidak boleh kehilangan suaranya ketika ketidakadilan struktural, ketimpangan kuasa, atau kerusakan ciptaan mulai mengancam kehidupan umat. Diam yang terlalu cepat demi stabilitas sering kali melukai lebih dalam daripada konflik yang jujur.
Dalam kehidupan internal Gereja, setiap keputusan pastoral, termasuk pengelolaan sumber daya dan penataan pelayanan, dipanggil untuk mencerminkan wajah Kristus yang gembala. Transparansi, dialog, dan kepekaan terhadap perasaan umat bukanlah kelemahan kepemimpinan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Umat tidak hanya membutuhkan penjelasan yang benar, tetapi juga pengakuan atas kegelisahan dan ketakutan mereka.
Gereja yang sinodal adalah Gereja yang mau berhenti sejenak, mendengarkan, dan belajar. Kritik yang lahir dari cinta akan Gereja bukan ancaman, melainkan rahmat. Dalam konteks Papua, suara masyarakat adat, para imam, kaum muda, dan perempuan harus dipelihara sebagai bagian dari proses pembedaan roh bersama, agar keputusan-keputusan Gereja sungguh menjadi jalan kehidupan, bukan sumber luka baru.
Akhirnya, refleksi pastoral ini mengajak kita semua, gembala dan umat untuk kembali pada pertanyaan Injil yang sederhana namun menuntut keberanian: Apakah langkah-langkah yang kita ambil sungguh menghadirkan Kristus yang membela kehidupan, menjaga ciptaan, dan mengangkat martabat yang kecil? Bila jawaban itu masih samar, maka Gereja dipanggil bukan untuk membenarkan diri, melainkan untuk terus berjalan, mendengarkan, dan bertobat bersama.
Sebab hanya Gereja yang mau berjalan bersama umat di tanah yang terluka, yang dapat menjadi tanda harapan di tengah dunia. (*)
*) Penulis adalah Pemerhati Gereja Katolik
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!























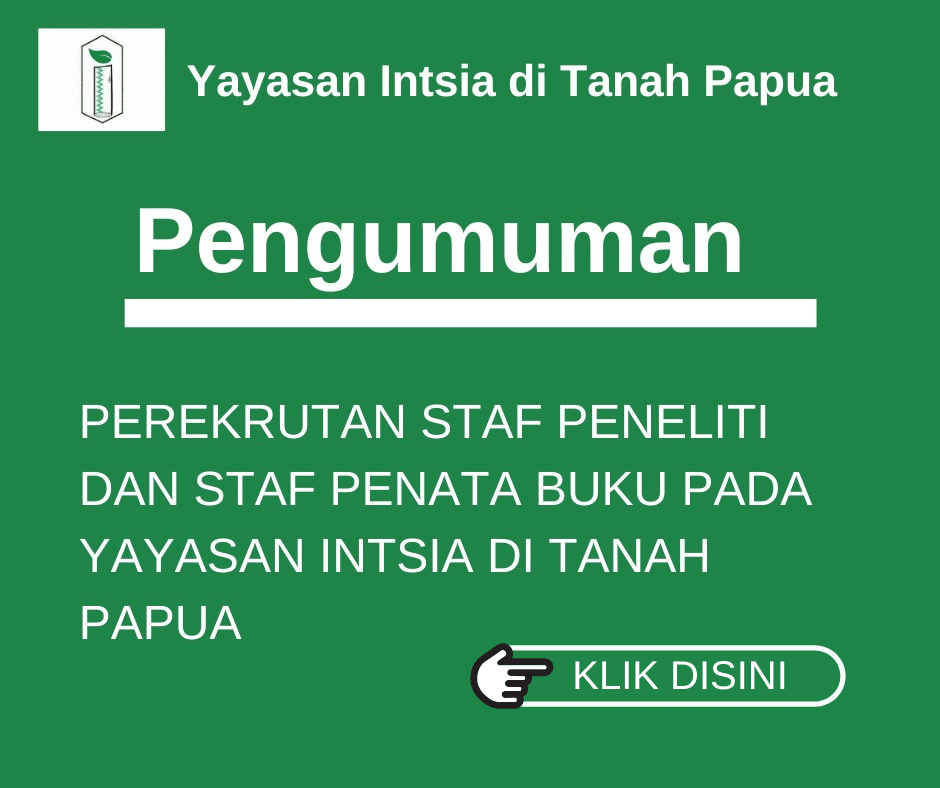



Discussion about this post