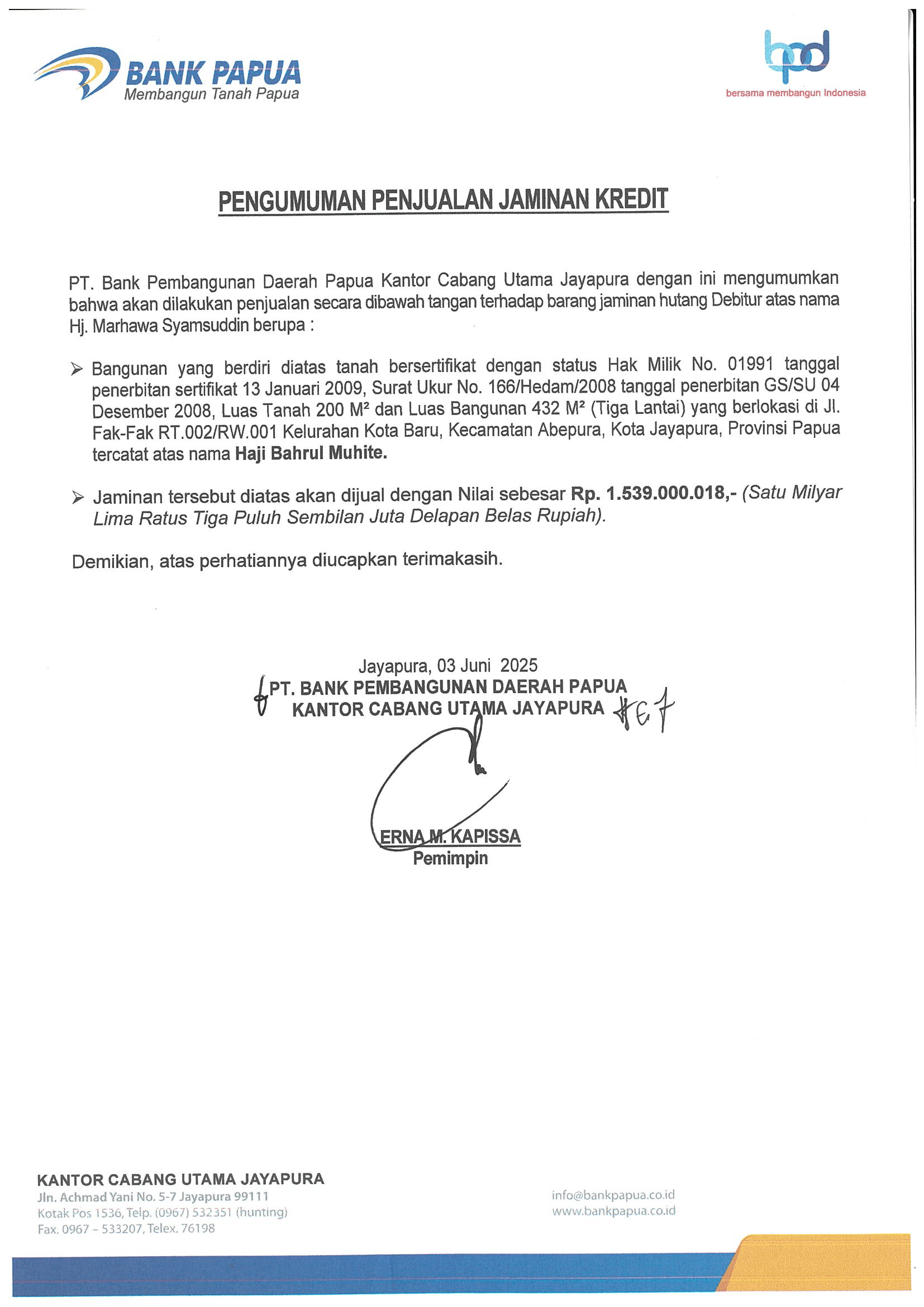Oleh: Siorus Degei
Motivasi penulisan artikel Angganeta Manufandu dan Yosepha Alomang ini muncul ketika banyak perempuan milenial Papua yang mulai sadar dan memperjuangkan nasib bangsa dan gender yang terpasung budaya bahkan ideologi patriarki, yang sudah berurat berakar dalam kehidupan di Tanah Papua. Apalagi perjuangan perempuan Papua yang dipantik oleh paham-paham feminisme moderat dan radikal semakin mengkristal pasca peluncuran buku “Perempuan Bukan Budak Laki-Laki” karya Pendeta Socratez S. Yoman dan “Perempuan Bukan Tulang Rusuk dan Penolong”.
Buku-buku itu sempat trending dan menuai pro-kontra di kalangan pembaca Papua. Pihak yang pro (mayoritas perempuan dan penganut paham feminisme marxis) mengklaim bahwa buku tersebut semacam “membakar jenggot” kaum adam di Papua.
Sebaliknya kaum adam di Papua menilai bahwa buku itu sangat subjektif karena hanya berisi opini-opini pribadi Pendeta Yoman sendiri tanpa studi kasus yang kompleks, komprehensif, dan ilmiah. Buku itu juga dianggap provokatif karena melaluinya terjadi distingsi, dikotomi, dan gab besar antara kaum adam dan hawa di Papua, terutama di kalangan aktivis HAM).
Mereka yang kontra dengan buku tersebut juga menganggap bahwa buku yang ditulis Pendeta Socratez itu sebagai komoditi-ekonomis, karena dibuat tergesa-gesa, sangat tidak mendidik kaum masyarakat yang rasio buta huruf, literasi, dan digitalnya sangat terpuruk. Akan tetapi, demi bisnis buku dan kebutuhan finansial buku itu dicetak dan dipropagandakan.
Buku ini juga dianggap diskriminatif sebab mengerdilkan eksistensi laki-laki Papua. Bahwa tidak semua laki-laki Papua bertindak demikian. Dan buku ini juga dianggap sebagai sebuah “pseudo inteletual” karena tidak ada kajian ilmiah yang sahih dan mendukung argumentasi pendeta dalam bukunya.
Penulis buku juga terkesan hanya copot sana-sini dan berbagai sumber (discovery), bukan hasil temuan sendiri yang baru (invention). Lagi pula materi yang beliau angkat ini bukan substansi persoalan West Papua—sebab masalah utama di Papua murni status politik dan HAM, bukan kesetaraan gender semata.
Berkaca dari debat kusir seputar buku pendeta Socratez yang terkesan hanya menyinggung kasus “remeh-temeh” tanpa menggubris sama sekali intisari persoalan Papua, penulis buku dan semua pihak yang terlibat dalam diskusi kusir hanya mengorek asap konflik Papua, tanpa membenahi tungku dan bara api konfliknya.
Mereka terjerumus dalam “irama dangdut saweran Jakarta” tanpa memainkan musik “Mambesak dan Black Brohters” atau masuk dalam “skenario intelijen NKRI” yang hendak “mempolarisasi, mensegmentasi, dan mensegregasi” bangsa Papua dari entitas yang besar, seperti, tujuh wilayah adat, denominasi gereja-gereja, kabupaten/kota (DOB dan Otsus), suku-suku, marga-marga, sub-marga versus sub-marga, pandangan politik, ideologi dan nasionalisme (NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati), hingga akhirnya distingsi dan dikotomi antara laki-laki dan perempuan Papua.
Fenomena di muka semakin kritis dengan hadirnya angin feminisme marxis yang hendak dipropaganda, dikonsolidasi, sosialisasi dan diedukasi di Papua, dengan sasaran kaum milenial Papua, khususnya perempuan dan laki-laki muda Papua yang berjiwa feminis sejak secara alami (punya kedekatan emosional yang khusus dengan perempuan atau anak mama).
Sebenarnya motivasi perjuangan feminisme marxis ini baik, sebab perjuangan feminisme menjadi opsi dan garda penting yang mereka kawal bersama, dalam agenda revolusi di hampir semua wilayah.
Namun, pada kesempatan ini penulis hendak “mempurifikasi dan mengkristalisasi” ideologi feminisme marxis (moderat dan radikal) yang dibawa masuk ke Papua. Penulis mengajak para pejuang feminisme marxis ini agar mahir dalam metodologi “kontekualisasi, relevansi, korelasi, dan internalisasi nilai”. Singkatnya metode “kawin-mawin teori dan praktik ilmiah”.
Bahwa ideologi baru (sebenarnya bukan baru) yang hendak dikonsolidasikan itu ibarat “bahan makan mentah”. Orang Papua itu ibarat “seorang bayi” dalam kacamata indeks pertumbuhan dan perkembangan budaya literasi dan digital, sehingga para pejuang feminisme marxis ini mesti tampil seperti seorang “ibu yang baik”.
Ibu yang baik selalu berkeinginan agar anaknya tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti. Ia akan memberikan makanan bergizi bagi anaknya.
Dalam artian bahwa ideologi feminisme marxis yang hendak dibawa itu mesti “dikontekstualisasikan, direlevansikan, dikorelasikan, dan diinternalisasikan”dengan niai-nilai luhur dalam adat, agama dan lingkungan sosial-ekonomi-politik-budaya di Papua.
Pendek kata, ideologi feminisme marxis itu mesti “dikawinkan dengan teks dan konteks habitat Papua dan kepapuannya”.
Artikel ini adalah seinci upaya penulis dalam meletakkan perjuangan kawan-kawan pejuang feminisme marxis di Papua itu, pada koriodor perjuangan emansipasi perempuan Papua yang sudah ada sejak Mama Angganeta Manufandu hingga kini Mama Yosepha Alomang.
Penulis mengajak para pejuang feminisme marxis untuk “mengkotekstualisasikan” atau “mengawinkan” pandangannya dengan spirit perjuangan perempuan Papua yang sudah ada, yakni “perjuangan emansipasi perempuan” atau “perjuangan spiritual mama-mama Papua”.
Hal ini penting agar perjuangan pergerakan feminis yang sedang jalan ini tidak “kena kosong” atau “salah sasaran”, tetapi “kena konteks” atau “tepat sasaran”.

Mama Angganeta Manufandu: Pelopor emansipasi perempuan Papua
Mama Angganeta Manufandu lahir pada 1905 dan dibaptis dengan nama Angganeta pada 25 September 1932. Ia adalah perempuan asli Papua asal Supiori dari Kampung Sowek, Kepulauan Insobabi. Perempuan ini dikenal dengan sebutan “Bin Dame”, karena ia pembawa damai.
Ia terlahir dengan nama asli Angganeta Menufandu yang dalam adat disebut “inseren sowek“. Ia juga seorang guru agama Kristen.
Suatu ketika ia melihat kekejaman bangsa asing (Jepang dan Belanda) di kampung halamannya. Ia merasa bahwa kekejaman penjajah asing yang brutal, fatal, dan radikal itu tidak boleh dibiarkan.
Kemudian pada 1938 ia memimpin Gerakan Koreri (Koreri berasal dari Bahasa Biak yang secara etimologi berasal dari “ko” (kita) dan “rer” (ganti kulit).
Untuk mengubahnya menjadi kata sifat diberikan imbuhan huruf “i”, maka disambung menjadi Koreri. Makna koreri secara luas adalah “kita menjadi baru kembali”. Koreri bersumber dari mitologi perjalanan Mananermarkeri yang dikenal sebagai Kayan Biak atau Kayan Sanau. Laki-laki tua yang kudisan dan kaskado bisa berubah kulitnya menjadi bersih.
Bersama Gerakan spiritual perdana di Papua itu Mama Angganeta Manufandu angkat senjata untuk memukul mundur penjajah asing—Belanda dan Jepang itu (Jubi.id, 23/4/2022). Bersambung. (*)
Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura, Papua

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!