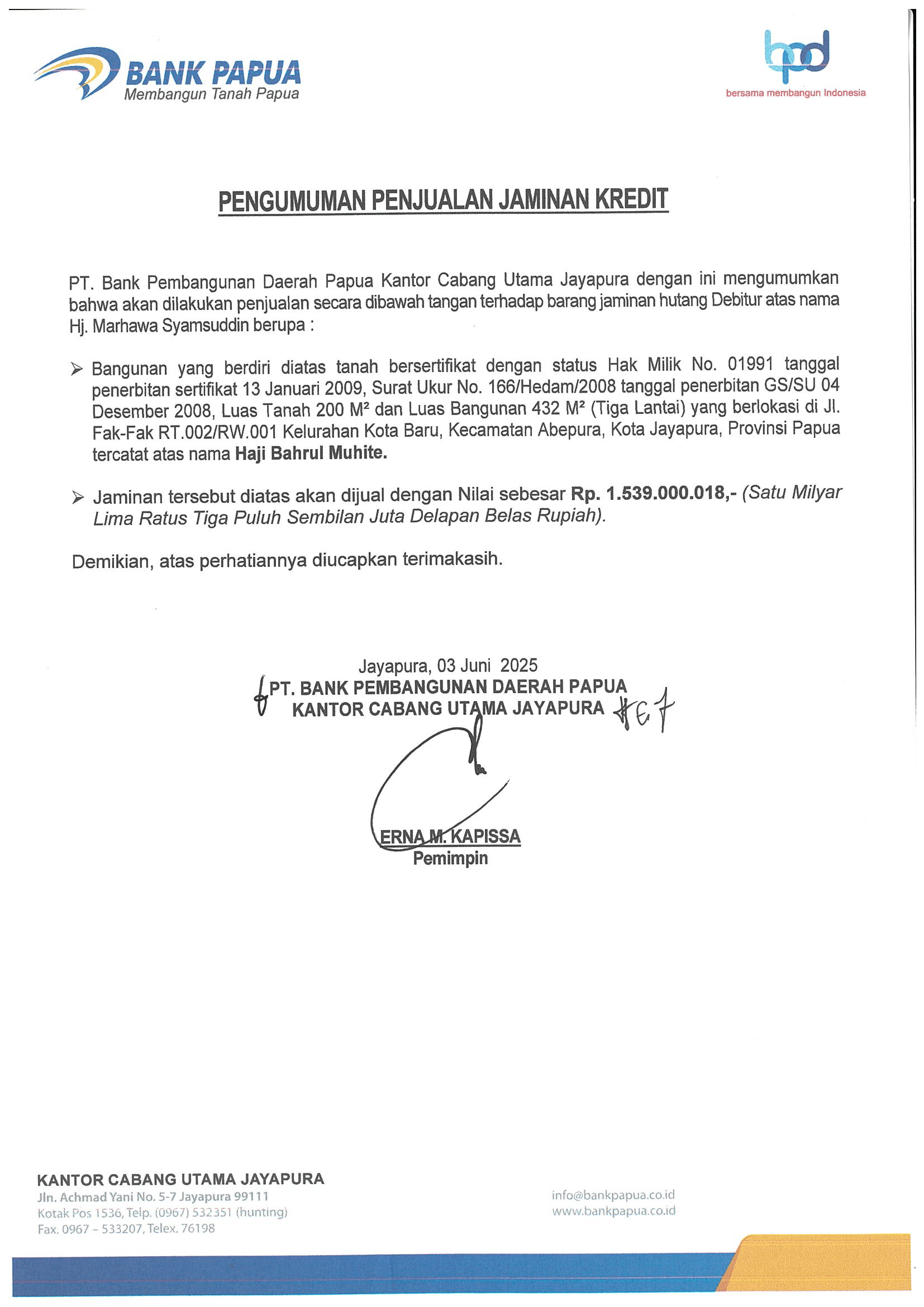Jayapura, Jubi – Antropolog Dr. Agr Laksmi Adriani Savitri, M.Si., menyebut bahwa orang Marind Anim adalah kelompok pertama di Bumi Animha yang berinteraksi dengan orang asing.
“Kedatangan mereka tentu sulit dibedakan, apakah sebagai kawan atau lawan, di tengah interaksi dengan berbagai etnis,” katanya kepada Jubi.id pekan lalu di Merauke.
Sejak masa lampau, wilayah ini telah menerima berbagai kedatangan, mulai dari program kolonisasi era Belanda hingga transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. “Saat ini, wilayah ini juga menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional,” tambahnya.
Tak hanya manusia, berbagai spesies asing juga diperkenalkan ke wilayah ini, salah satunya adalah rusa. Mamalia ini menjadi ikon Merauke, yang kini dijuluki sebagai Kota Rusa.
“Rusa bukan hewan mamalia asli Merauke,” ungkap Dr. Budi Darmawan, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, dalam sebuah diskusi di Gedung Petrus Vertenten, Merauke. “Hewan ini berasal dari luar Papua.”
Dalam bukunya Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya, pakar lingkungan Prof. Dr. Ronald G. Petocz mencatat bahwa rusa (Cervus timorensis) diperkenalkan oleh Belanda pada 1928. Populasinya berkembang pesat di Tenggara Papua Selatan hingga Papua Nugini.
“Saat itu, rusa diburu secara besar-besaran,” tulis Petocz. Kini, pemerintah Indonesia telah melarang perburuan satwa tersebut.
Menurut Buletin Kabar dari Kampung (KdK) Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD), kontak pertama orang Marind Anim dengan orang asing terjadi pada 15 Oktober 1892, saat Pos Pemerintahan Belanda dibuka di Kampung Serilika.
Kontak berikutnya terjadi pada 1902, ketika Pastor Carlos van der Heydem, S.J., dan Komandan Abe mendirikan pos pelabuhan di Kota Merauke.
Pada 21 Februari 1902, sekelompok orang dari Pulau Jawa tiba di Merauke, mengikuti perjalanan orang-orang Belanda dengan kapal uap Van Doorn. “Ini adalah kontak ketiga antara orang Marind dan orang asing,” tulis KdK.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak misionaris dan kelompok pendatang yang tiba di wilayah ini. Pastor Mathias Neyens, yang datang pada 1904, memimpin misa pertama pada 19 November 1905.

Pada 1908, pemerintah Belanda kembali mendatangkan orang Jawa dan menempatkan mereka di Kuprik. Pada tahun yang sama, 47 orang dari Pulau Rote tiba di Merauke, memperkenalkan minuman saguer dan sopi yang diolah dari pohon kelapa kepada orang Marind.
Dua tahun kemudian, orang-orang Jawa kembali didatangkan dan ditempatkan di Spadem serta Mopah Lama. Mereka bertani, membuka sawah, dan beternak untuk mendukung kebutuhan pegawai pemerintah Belanda.
Rusa pertama kali diperkenalkan pada 1913, kemudian pada 1920 dan 1928, sebagaimana dicatat oleh Petocz.
Pada 1913, terjadi wabah penyakit kelamin yang menyerang masyarakat Marind Anim. Penyakit ini menyebar akibat pergaulan bebas dan ritual tertentu.
Pada 1914, pemerintah Belanda mengirim dokter Sitanalah ke Merauke untuk mengobati masyarakat yang terjangkit. Baru pada 1921 penyakit ini diidentifikasi sebagai penyakit kelamin.
Untuk mencegah penyebaran, pada 1917 pemerintah menempatkan 20 kepala keluarga (KK) Marind yang masih sehat di sebuah desa khusus. Pada 1919, jumlah ini bertambah menjadi 100 KK.
Max Mahuze, tokoh masyarakat yang kini menetap di Muting, memperkirakan bahwa hampir 40 persen populasi Marind Anim kala itu meninggal akibat wabah ini.
“Artinya, hanya sekitar 60 persen yang tersisa, sementara sumber daya alam tetap melimpah,” kata Mahuze.
Pada 1925, guru-guru katekese dari Kei dan bruder dari Belanda datang ke Merauke. Pada tahun yang sama, para pedagang luar mulai berdagang dengan masyarakat setempat, memperkenalkan barang seperti pisau, celana, dan kain kebaya.
Pada 1943, pemerintah Belanda meneliti tanah di sekitar Sungai Digul, Bian, dan Muting untuk pengembangan pertanian. Namun, penelitian ini terhenti karena pendudukan Jepang pada 1942.
Pasca Perang Dunia II, Belanda kembali menjalankan proyek persawahan di Kumbe dan Kuprik, mendatangkan orang Jawa ke Merauke. Dari sinilah muncul istilah Jamer (Jawa Merauke).
Setelah Belanda hengkang, pemerintah Indonesia melanjutkan program transmigrasi. Pada Pelita III (1978–1982), sebanyak 5.306 KK atau 21.582 jiwa ditempatkan di 13 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Merauke. Jumlah ini bertambah pada Pelita IV dan V hingga mencapai puluhan ribu jiwa.
Memasuki era reformasi, masyarakat Marind Anim mulai menolak program transmigrasi, terutama di Sota I Merauke yang berbatasan dengan sumber air minum Rawa Biru.
Pada 1980-an, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mulai masuk ke Merauke, mencakup lahan seluas 3,8 juta hektare di wilayah yang saat itu meliputi Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
Pada 2010, proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diluncurkan dengan luas 1,2 juta hektare. Kini, proyek tersebut berkembang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luasan mencapai dua juta hektare.
Rencana ini mendapat penolakan keras dari masyarakat adat Papua Selatan. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!