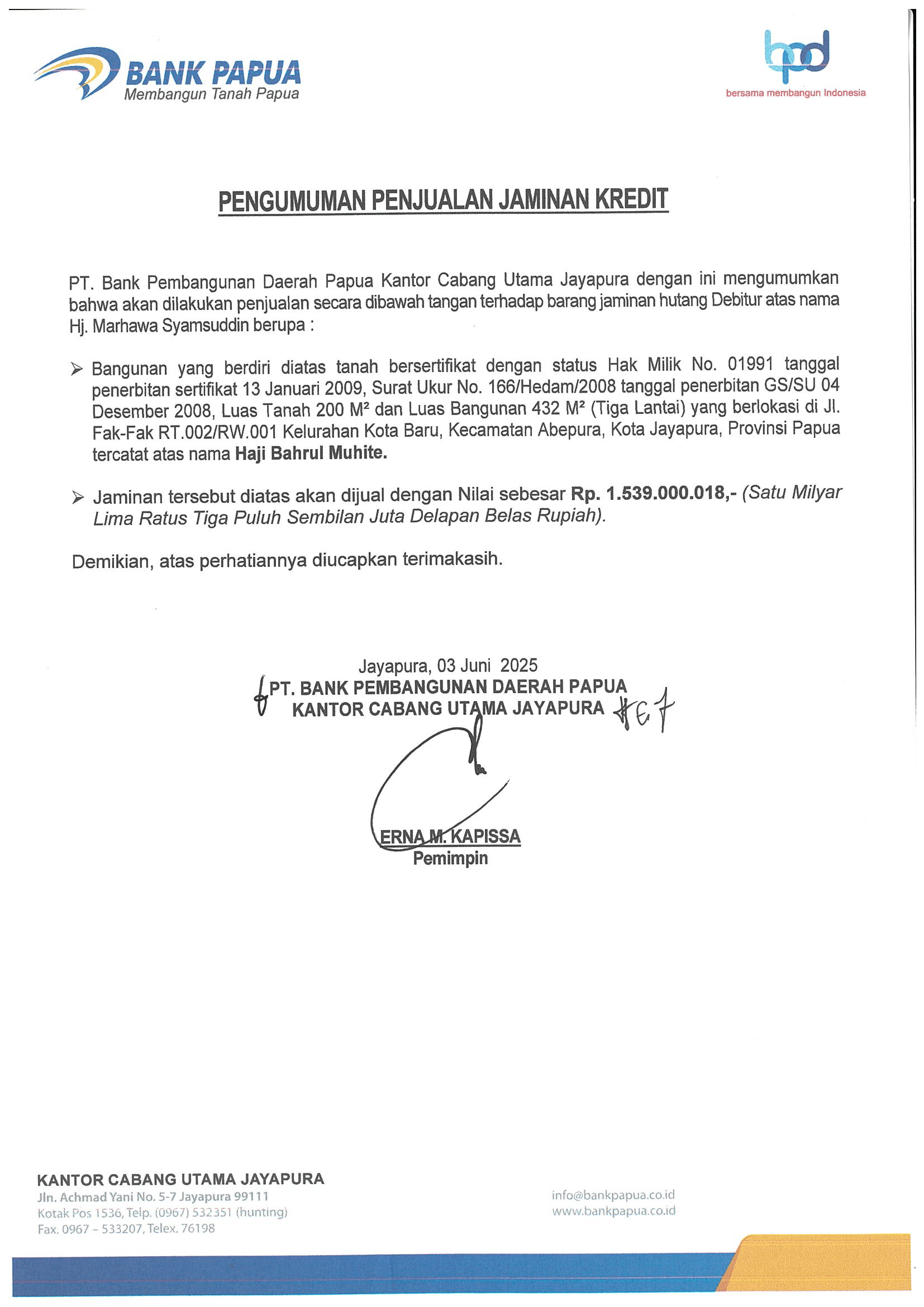Reporter: Theo Kelen, Rabin Yarangga, Dominggus A Mampioper, Angela Flassy
Timika, Jubi – Aktivitas tambang PT Freeport Indonesia sejak 1972 telah mengubah gunung menjadi jurang raksasa, menggerus dan melumat batuan kaya mineral emas, dan membuang “sisa” batuannya ke sungai di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sisa batuan disebut tailing itu mendatangkan rejeki bagi ribuan pendulang, namun juga menimbulkan pendangkalan sungai dan pesisir Mimika. Jubi dan CNN Indonesia berkolaborasi meliput beragam cerita keberadaan tailing PT Freeport Indonesia, baik sebagai pembawa rejeki ataupun sebagai pembawa masalah. Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari tiga laporan kolaborasi peliputan tersebut.
[iframe https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1dAXmGcG-bO3_5H-M19urt2Pya3vHYDM&ehbc=2E312F 640 480]Siang itu, Alexander Matiwera sedang sibuk membenahi atap dapurnya yang bolong. Daun nipah yang dijalin menjadi atap dapur sebuah rumah di Kampung Ohotya, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, itu melapuk dimakan usia.
Lelaki 51 tahun itu ditemani keluarganya. Yustina Tawapi (45), istri Matiwera, menganyam lembaran demi lembaran daun nipah menjadi atap. Sementara anak-anaknya tampak cekatan menyiapkan tali yang akan digunakan untuk mengikat daun nipah menjadi atap dapur mereka. “Butuh tiga lapis biar [atap] kuat,” kata Matiwera.
Matiwera bersama keluarganya menempati sebuah rumah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mimika di Ohotya, sebuah kampung yang juga dikenal dengan nama lain, Kampung Otakwa. Ia mendapat rumah bantuan itu gara-gara rumahnya di kampung lama, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi rumahnya sekarang, hancur diterjang ombak.
“[Kami] mulai pindah dari kampung lama [tahun] 1999. Dulu bangunan rumah [lama kami] pakai kayu, dinding pakai gaba sagu, atap pakai daun pohon nipah. Ini pemerintah masuk [memberi bantuan], baru ada [rumah beratap] seng. Rumah [yang ditempati masyarakat] sekarang ini dibantu pemerintah,” ujarnya.

Rumah bantuan itu adalah rumah panggung beratap seng dan berdinding papan, tanpa dapur. Matiwera membangun sendiri dapurnya, yang siang itu ia perbaiki lantaran atap daun nipahnya telah usang.
Di Ohotya, Matiwera tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Atofianus Matiwera (21), anak sulung Alexander, telah menikah dan membawa istrinya yang bernama Hermina Matanimi tinggal di rumah yang sama.
“Kitorang dari Timur, [kami] dulu [menyebut diri kami] Suku Sempan. Sekarang [orang] bilang [kami adalah orang Suku] Kamoro, padahal [kami memiliki perbedaan] bahasa. Kitorang [tetap menyebut diri kami orang] Sempan timur,” tutur Alexander Matiwera.
Kampung Ohotya jauh dari segala hiruk-pikuk Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika yang seluruh geliat kehidupannya berporos kepada aktivitas tambang PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk datang ke Ohotya, kami menempuh perjalanan mobil selama satu jam dari Timika menuju Pelabuhan Pomako.

Dari Pelabuhan Pomako, kami melanjutkan perjalanan dengan kapal kecil yang digerakkan mesin bertenaga kuda 80 PK, menyusuri kelokan sungai dan hutan bakau selama satu jam menuju pesisir Puriri. Dari sana, kami menyusuri tepian Laut Arafuru yang bergelombang besar. Setelah tiga jam menyusuri pesisir itu, barulah kami sampai di Ohotya.
Sehari-hari, kehidupan Matiwera dan keluarganya tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat Kamoro lainnya, sebuah suku masyarakat adat di pesisir Mimika yang terdampak aktivitas tambang PTFI. Setiap pagi, Matiwera harus mendatangi tempat penampungan air hujan di Kampung Ohotya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya. “[Setiap hari saya bangun] jam 05.00 WP, lalu isi air di drum,” ujarnya.
Seperti kebanyakan orang Kamoro, Alexander Matiwera hidup dengan mengumpulkan bahan pangan dari alam. Orang Sempan, begitu pula orang Kamoro, adalah masyarakat adat yang hidup dari aktivitas berburu, menangkap ikan, dan meramu—mengandalkan penghidupan dari apa yang alam sediakan tanpa perlu bercocok tanam atau budidaya.
Jika tiba masa mencari makan, Alexander Matiwera akan meninggalkan rumahnya selama dua hingga tiga hari untuk menyusuri pesisir, menjaring ikan duri dan ikan kapan di perairan payau muara Sungai Ohotya. “Kalau nasib baik, bisa dapat 150 kilogram [ikan. Kalau sedang sial] paling sedikit [saya dapat tangkapan] 10 kilogram [ikan],” ujarnya.

Ia mengeluh semakin sering mendapat tangkapan ikan yang terlalu kurus, atau ikan berbadan sedang namun berkepala kecil. Menurutnya, ia semakin sering mendapati ikan tangkapan seperti itu sejak sedimen tailing atau pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia memasuki perairan Ohotya.
“Ada yang kurus kitorang [tidak jual dan] tidak makan. Kalau gode [atau besar], kitorang makan [dan jual]. [Ada ikan yang] kepalanya besar, badannya kecil. Jadi mungkin tercemar kah apa? Kitorang tidak tahu. Dulu tidak begitu. Dulu semua aman, ikan sehat, gemuk. Kalau sekarang kurus. Biasa kitorang pilih, kalau kurus kitorang buang saja begitu,” ujarnya.
Matiwera menyatakan ikan tangkapannya biasa dijual kepada pengepul atau pengusaha yang datang membeli di Kampung Ohotya. Ikan duri dijual dengan harga Rp6 ribu per kilogram, sementara ikan kakap dijual dengan harga Rp17 ribu per kilogram. Sementara kepiting biasa dijual sesuai ukuran, dengan kisaran harga Rp10 ribu hingga Rp40 ribu per ekor.
Jika sedang beruntung, dari tangkapan ikan selama dua atau tidak hari itu, Matiwera bisa mengantongi Rp2 juta. Hasil penjualan ikan itu dipakai untuk kebutuhan makan dan minum, serta biaya pendidikan anak-anaknya. Matiwera kesulitan untuk menjual ikan tangkapannya langsung ke Pelabuhan Pomako, karena ongkos perjalanan dari Ohotya ke Pomako bisa memakan uang Rp980 ribu. Ombak besar Laut Arafuru juga memikin jeri, karena bisa membalik perahu yang menyusuri pesisirnya.
Didera banyak masalah
Kepala Kampung Ohotya, Kabupaten Mimika, Bernadus Irahewa menyebut sedimentasi tailing atau pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) memang berdampak kepada kehidupan dan penghidupan 154 kepala keluarga di Kampung Ohotya. Irahewa menyatakan tailing yang dibuang PTFI melalui Sungai Ajkwa mengalir sejauh 120 kilometer ke Laut Arafuru.
Di perairan lepas sedimen tailing terbawa gelombang pasang surut hingga ke mana-mana, membuat pasang-surut lebih cepat mendangkalkan muara sungai, termasuk Sungai Ohotya. Irahewa menuturkan pendangkalan itu secara perlahan-lahan membuat masyarakat adat di pesisir Mimika kehilangan tangkapan ikan. “Ikan habis. Kali yang dulu besar, [sekarang] tanah tailing yang di atas,” ujarnya.
Menurut Irahewa air pasang yang bercampur sedimen tailing itu membuat pohon sagu rusak, bahkan mati. Padahal sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat adat Sempan maupun Kamoro. Jika diolah menjadi tepung sagu, pohon sagu di Ohotya menghasilkan endapan tepung bertekstur kasar kehitaman, dan aromanya pun tak sedap.
“Pohon sagu [kami] sudah tidak layak, namun masyarakat masih paksa untuk konsumsi. [Tepung] sagu yang dulu bisa tahan satu bulan, sekarang tidak bisa. Seminggu atau dua minggu dalam rumah, sudah tidak layak [dikonsumsi]. Bukan busuk, tapi macam jadi keras dan baunya sudah [tidak enak]. Dusun sagu [kami] masih ada, cuma [sagunya] tidak seperti yang dulu,” ujarnya.

Irahewa menyatakan tailing sangat menyusahkan masayarakat pesisir Mimika seperti yang dirasakan masyarakat di Kampung Ohotya. Ia menyatakan tailing sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Ohotya. Ia pun merasa heran karena kerap mendengar pejabat atau tokoh yang menyebut tailing PTFI bermanfaat.
“Bagi kami masyarakat, yang kami tahu itu merugikan kami. Tailing untungnya apa, kami tidak tahu. Itu pemerintah yang tahu, pemerintah mau olah, instansi terkait yang bisa olah [tailing], ya [silahkan] olah. Kami masyarakat biasa tidak tahu, yang kami tahu tailing itu menyusahkan kami,” ujarnya.
Irahewa mencontohkan, susahnya perjalanan warga Ohotya yang ini pergi ke Timika melalui Pelabuhan Pomako. Irahewa menuturkan dulu masyarakat bisa menyusuri Sungai Khuhaireipey, lalu menuju Sungai Yamawiripa, dan menyusuri Sungai Yamaima hingga tembus di Sungai Hafuka. Selepas itu, mereka tinggal melewati Pulau Karaka dan sampai di Pelabuhan Pomako. “Tapi sekarang [jika] kami [ingin ke [perairan lepas] pantai [Pulau Karaka menuju Pomako] itu kita baku tanya dulu, tailing [akan muncul ke permukaan laut ketika air surut],” ujarnya.
Irahewa menyatakan walaupun warga Kampung Ohotya hidup dalam keterbatasan dan ancaman, masyarakat tetap memilih bertahan hidup di Kampung Ohotya. “[Kami] tidak bisa untuk pindah, karena kampung [kami adalah] tanah adat dari leluhur,” tuturnya.
Padahal hidup di Ohotya tidaklah mudah. Daniel Bipoaro (51) masih ingat bagaimana jernihnya air Sungai Ohotya, Sungai Hetia, dan Sungai Momoa yang sejak dahulu menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Ohotya. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an, air ketiga sungai tidak lagi layak dikonsumsi.
“Air di tiga kali itu sudah tidak layak digunakan. Air jernih sudah tidak ada. Mau ambil di kali itu sudah tidak bisa, [karena] memang kabur betul,” katanya.

Seperti Alexander Matiwera, Bipoaro pun mengadalkan air hujan untuk memasak maupun konsumsi sehari-hari. Untuk mencuci dan mandi, keluarga Bipoaro memakai air sumur yang terasa payau.
Apabila persediaan air hujan telah habis, Bipoaro dan warga Ohotya lainnya harus memacu perahu mereka sejauh 30 kilometer untuk mencari air di rawa-rawa maupun di kali sekitar Sungai Ohotya, Sungai Hetia, dan Sungai Momoa.
Air sungai di muara juga semakin tidak bersahabat dengan anak-anak Kampung Ohotya. Irahewa menuturkan anak perempuannya, Semona Irahewa (11) menderita penyakit kulit yang gatal sejak Oktober 2022. Di wajah Semona ada banyak bentol, dan kedua tangannya juga dipenuhi ruam dan bentol.
Irahewa harus berkala membawa anaknya berobat ke Rumah Sakit Caritas Satuan Permukiman atau SP 5. “Kadang hilang terus muncul lagi [itu gatal]. Kami [hanya bawah mereka berobat] di Pustu,” ujarnya.

Kondisi yang sama juga dialami Bas Karewa. Orangtuanya, Agustina Bipora mengaku gejala itu muncul setelah anaknya mandi di tepi laut sekitar kampung.
“[Saya] bawa [dia] berobat ke Pustu saja. Dong [petugas kesehatan] kasih Amoxcilin dan Ampicilin,” kata Agustina.
Ananias Kawera yang sudah menjadi siswa SMA Taruna Pelayaran Mimika juga mengalami penyakit kulit di tangan, paha, hingga ke kakinya. Kawera mengaku gatal-gatal itu muncul seusai ia mandi air laut. “Mandi di laut, pulang gatal sampai bengkak. Rasa gatal [semakin menjadi] saat malam hari,” kata Kawera.
Petugas Kesehatan Puskesmas Pembantu Kampung Ohotya, Polce Irahewa (30) menyatakan anak-anak di Kampung Ohotya mulai mengalami penyakit kulit itu sejak Desember 2022. Ia menduga gatal-gatal itu disebabkan lingkungan yang kotor.
“Beberapa tahun yang lalu tidak seperti itu. [Sekarang] mandi air laut itu langsung gatal,” kata Polce yang sejak Desember 2022 sudah menangangi sekitar 30 anak-anak yang menderita penyakit kulit.
Terdampak sejak lama
Dosen antropologi Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dr Hanro Yonathan Lekitoo menyatakan masyarakat adat Sempan di Ohotya merupakan bagian dari masyarakat adat Kamoro. Menurut Lekitoo, hal itu terlihat dari pola kehidupan yang sama dengan masyarakat Kamoro umum lainnya.
“Mungkin mereka punya bahasa agak beda. Tetapi mereka bagian dari satu rumpun yang punya mata pencarian itu sama. Cara kehidupan meramu, menangkap ikan, [dengan hidup yang berporos kepada] 3S, yakni ‘sungai’, ‘sampan’, dan ‘sagu’. Itu masih dominan di Otakwa, sama dengan masyarakat Kamoro di Timika,” ujarnya.
Wakil Ketua II Lembaga Masyarakat Adat Kamoro atau Lemasko, Siprianus Operawiri menyatakan dahulu masyarakat adat dari Ohotya, Umuga, dan Inoga yang mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Distrik Mimika Timur Jauh sempat direlokasi di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika.
“Masyarakat dari [Mimika] Timur Jauh—yaitu Otakwa/Ohotya, Umuga, Inoga—dipindahkan ke Timika [bersama-sama masyarakat adat dari Kampung] Koperapko, Nawaripi dan Negeripi. Lokasi [permukiman masyarakat adat Mimika Timur Jauh di Kota Timika] itu yang sekarang namanya Sempan. Akan tetapi, masyarakat Sempan mereka kembali lagi ke kampung halaman mereka,” ujar Operawiri.

Sejak lama, Masyarakat adat Kamoro dan Sempan terdampak sedimentasi tailing PT Freeport Indonesia. Operawiri mencontohkan wilayah Koperapoka Lama yang membentang mulai dari Kali Kopi di Distrik Kuala Kencana hingga ke wilayah pesisir Pantai Koperapoka. Di Koperapoka Lama dulu terdapat dua kampung, yakni Kampung Waunaripi dan Negeripi. Masalah keamanan membuat masyarakat dari dua kampung itu berpindah ke Pasir Hitam pada 1977, dan menetap di sana hingga 1980.
“Pada 1981, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia mulai merelokasi 900 kepala keluarga di sana, lantaran daerah Pasir Hitam terdampak tailing. Pemerintah Kabupaten dan Freepot sudah analisis dampak ke depannya seperti apa. Masalah pendangkalan atau kerusakan hak ulayat karena tailing penambangan Freeport,” kata Siprianus Operawiri.
Operwairi menyatakan setelah dipindahkan ke Timika, Kampung Waunaripi dan Negeripi dilebur menjadi satu kampung bernama Kampung Koperapoka. Pada 1993, seluruh warga tersisa di Kampung Koperapoka Lama direlokasi, dan Kampung Koperapoka yang baru dimekarkan menjadi tiga kampung, yakni Kampung Nawaripi, Nayaro dan Koperapoka.
“Pada saat itu, dengan adanya Dana Rekognisi, Freeport bangun perumahan dan bantuan ekonomi. Freeport kasih motor tempel 40 PK perkeluarga. Perumahan ini [diberikan] kosong, perabotnya tidak ada. Sampai sekarang [masyarakat] tiga kampung masih menetap di Timika,” ujarnya.

Akan tetapi setelah 30 tahun tinggal di permukiman baru kehidupan masyarakat Kamoro jauh dari sejahtera. Operawiri menyatakan sedimentasi tailing mulai menyebabkan kerusakan di daerah aliran sungai dan pesisir Kabupaten Mimika sejak 1991.
Menurutnya, tailing merusak hutan masyarakat adat Kamoro, termasuk Sempan. Masyarakat kehilangan lokasi berburu. Jalur sungai yang biasa dilalui masyarakat—seperti Sungai Amaufuruo, Muamiua, serta Sungai Ayua—menjadi dangkal dan dipenuhi endapan tailing. Bahkan sungai Amaufuruo sudah ditutup untuk penimbunan tanggul tailing.
Operawiri menyatakan tailing juga membuat beberapa jenis ikan seperti ikan pari, ikan mangiwang dan siput menghilang. Tailing juga membuat masyarakat adat kehilangan sumber air bersih. “Ikan tidak layak lagi untuk dimakan. Air minum dulu orangtua [ambil air] dari sungai sudah tidak bisa minum lagi. Itu akibat dari tailing, dampak langsung dari [tailing] Freeport,” kata Operawiri.
Operawiri membenarkan tailing juga menghancurkan dusun sagu masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Kampung Nawaripi. Masalahnya, setiap keret dan marga masyarakat adat terikat dengan tanah ulayatnya masing-masing, dan tidak bisa sembarangan mengambil hasil alam dari tanah ulayat milik keret atau marga yang lain. Masyarakat adat di Kampung Nawaripi kini harus membeli sagu di pasar.

“Masyarakat Nawaripi punya dusun sagu sudah tidak ada lagi. Dusun sagu banyak, [tetapi itu milik] per marga. Marga lain tidak bisa mengambil dusun sagu di marga lainnya,” tutur Operawiri.
Kehadiran PT Freeport Indonesia secara tidak langsung juga mengikis kehidupan masyarakat adat Kamoro yang tidak terlepas dari “sampan”, “sungai” dan “sagu”. Operawiri bersedih karena generasi muda Kamoro sudah tidak bisa membuat perahu tradisional berdayung panjang. Mereka tidak lagi berburu, dan tidak pula memangkur sagu (mengolah daging batang sagu untuk menjadi endapan tepung sagu).
“Anak muda kalau sekarang mau buat perahu sudah tidak bisa lagi atau tahu lagi. Perahu sendok [atau perahu tradisional, orang muda] sudah tidak bisa bikin,” ujar Operawiri.
Koordinator Komunitas Peduli Lingkungan Hidup atau Lepemawi di Timika, Adolfina Kuum menyatakan dampak tailing yang mendangkalkan sungai dan pesisir Mimika sangat mengorbankan masyarakat adat Kamoro. “Suku Kamoro ini punya kehidupan, ini dia punya tempat cari makan [di] laut, kali, Mama-mama dorang, aktivitas mereka lewat kali,” ujarnya.
Kuum juga menyebut pada 2016 dan 2020 ada ribuan ikan mati mendadak di Pelabuhan Amamapare, Wilayah Mimika Timur Jauh. “Komunitas mulai bergerak mulai bicara [masalah] itu. [Kami] prediksi 20 tahun ke depan masyarakat akan [semakin] susah,” ujarnya.
Semakin meluas
Pelan tetapi pasti, sedimentasi tailing PT Freeport Indonesia meluas di wilayah dataran rendah dan pesisir Kabupaten Mimika. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada 27 September 2022, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menyatakan pengolahan batuan bijih emas, perak, dan tembanga yang di tambang dari Grasberg tidak menggunakan merkuri maupun sianida, sehingga tailing buangannya tidak beracun. Akan tetapi, Tony mengakui bahwa volume tailing yang dibuang sangat besar, lebih dari 200.000 ton per hari.
“Tambang terbuka Grasberg sudah selesai ditambang pada 2019. Proses pengolahan [batuan bijih dari] tambang terbuka [Grasberg] ada batuan penutup yang harus dikupas dulu sebelum diambil bijih [mineral yang bernilai ekonomi]. Sementara di tambang bawah tanah, penambangan dilakukan dengan langsung mengambil bijih [mineral bernilai ekonomi], sehingga tidak ada dampak [berupa pembuangan tailing] batuan penutup,” kata Tony.
Tony menyatakan dalam pengolahan batuan yang ditambang dari tambang terbuka Grasberg dilakukan secara fisika menggunakan reagen sejenis alkohol untuk memisahkan mineral emas, perak dan tembaga dari batuan yang tidak bernilai ekonomis. “Sisanya, 97 persen yang merupakan [batuan dan] mineral tidak berharga dialirkan melalui sistem aliran sungai sesuai izin, dan ditempatkan di dataran rendah yang dinamakan area pengendapan Ajkwa. Tailing itu tidak beracun, namun volumenya sangat besar, di atas 200.000 ton per hari,” kata Tony Wenas dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI.
Tony Wenas juga menyatakan pembuangan tailing ke Sungai Ajkwa dan Otomona itu sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah. Ia meyebut deretan izin bagi PT Freeport Indonesia untuk membuang tailing ke dataran rendah Kabupaten Mimika, mulai dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Irian Jaya nomor 540/154/SET tertanggal 4 Januari 1995, SK Gubernur Irian Jaya Nomor 540/2102/SET tertanggal 20 Juni 1996, dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 300K Tahun 1997 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.—55/MENLH/12/1997.

PT Freeport Indonesia secara berkala memperbarui izin pembuangan tailing ke daerah aliran sungai dan pesisir Mimika itu, termasuk dengan mengantongi SK Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005. Freeport juga mengantongi SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 175/Menlhk/PLB.3/4/2018, SK Menlhk Nomor 594/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 berikut SK 101/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Berbagai deretan izin itulah yang dijadilan dasar bagi PT Freeport Indonesia untuk membuang tailing ke daerah aliran sungai dan pesisir Kabupaten Mimika. Kendati PT Freeport Indonesia menyatakan penambangan terbuka Grasberg telah berakhir dan penambangan bawah tanah tidak menimbulkan limbah tailing, volume limbah tailing yang ada di dataran tinggi wilayah pengendapan sangatlah besar, dan terus menambah sedimentasi tailing di dataran rendah hingga pesisir Kabupaten Mimika.
Ahli Penginderaan Jarak Jauh Universitas Indonesia, Sita Manessa yang diwawancarai CNN Indonesia menyebut sedimentasi tailing semakin meluas sejak 2000-an. “Kami mencoba mengamati di wilayah pesisir dan beberapa sungai besar di Mimika yang menjadi area pembuangan tailing. Mulai tahun 1990, sebetulnya proses pendangkalan dan sedimentasi secara pelan-pelan berlanjut. Akan tetapi, yang intensif terjadi sejak tahun 2000 sampai sekarang,” ujarnya.
Terlepas dari berlanjut tidaknya sedimentasi di dataran rendah dan pesisir Kabupaten Mimika, dampak pendangkalan daerah aliran sungai oleh tailing PT Freeport Indonesia telah dan terus terjadi. Kepala Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Arnoldus Natikapereau menyatakan wilayahnya terdampak tailing PT Freeport Indonesia sejak sekitar tahun 2000-an, ketika sungai-sungai di sana menjadi dangkal. Menurut Natikapereau, kedalaman Sungai Atuka yang semula mencapai 30 – 50 meter kini hanya berkedalaman 10 – 15 meter.

Natikapereau menyatakan sungai yang dangkal tidak mampu lagi menampung debit air pasang Laut Arafuru. Akibatnya, air pasang kerap merendam permukiman warga di tepi sungai atau berhadapan dengan Laut Arafuru seperti Kampung Atuka.
“Khususnya Kampung Atuka dan Kampung Amar, itu dalam posisi yang sama. Banyak terjadi kerusakan rumah karena debit air [pasang yang membuat] lantai rumah terangkat. Tahun 2022 lebih sadis, satu rumah ombak bongkar, delapan rumah rusak parah. Itu ombak pukul depan rumah,” kata Natikapereau.
Sebagaimana terjadi di Kampung Ohotya, 373 warga Kampung Atuka pun kehilangan sumber air bersih mereka. Dahulu warga biasa menggunakan air sungai dan air sumur untuk dionsumsi. Namun sekarang air sumur jadi kecokelatan dan payau, sehingga hanya dipakai untuk untuk mencuci perkakas dapur, mandi, atau mencuci pakaian.
Jika hujan tak lama turun, warga Atuka akhirnya terpaksa meminum air sungainya, atau membeli air bersih dari Pelabuhan Pomako. “Dulu kita minum air dari sungai, air dari sumur. Sekarang tidak bisa. Kami berharap cuma air hujan. Tadah air hujan pakai tandon atau tanki,” ujar Natikapereau.
Ia menuturkan arus dan arah gelombang pesisir Laut Arafuru kerap berubah-ubah, sehingga lokasi permukiman yang sebelumnya aman bisa hancur dihantam gelombang. Masalahnya, masyarakat adat di Atuka hanya bisa berpindah tempat tinggal di wilayah tanah ulayat mereka sendiri, yang semuanya rentan terdampak gelombang dengan arah berubah-ubah.

Natikapereau menuturkan lokasi Kampung Atuka saat ini merupakan lokasi kedelapan yang ditempati masyarakat Atuka. “Menurut cerita orang tua, ini merupakan kampung yang kedelapan. Tidak mungkin kami tinggalkan kampung. Kampung ini kami punya. Kami cuma merantau di kota cari kerja. Satu saat pasti akan pulang ke kampung,” ujar Natikapereau.
Pendangkalan sungai di pesisir Mimika itu membuat warga Atuka yang ingin berpergian dengan jalur sungai menyesuaikan diri dengan siklus pasang surut di sana. Mereka harus bepergian pukul 07.00 WP, karena pada pukul 12.00 WP air sungai akan surut dan membuat lunas perahu kandas, atau bahkan harus menggendong perahu karena dasar sungai telah muncul ke permukaan air sungai.
Jika harus bepergian pada siang hari, masyarakat harus memutar lewat jalur pesisir Laut Arafuru yang bergelombang besar. Tak banyak yang berani melakukannya, karena sebagian besar masyarakat hanya memiliki perahu yang digerakkan mesin berkekuatan tenaga kuda 40 PK.
“Walaupun kami orang pantai, tidak berani lewat laut, kami lewat sungai saja. Jadi kami kejar pas air pasang [untuk bepergian]. Kalau air sudah surut, tidak bisa lewat sama sekali. [Kalau] kami turun [turun dari perahu, ketinggian air] sampai dada saja. Kami bertahan saja, sambil menunggu air pasang, baru bisa lewat,” ujarnya.
Menurut Arnoldus Natikapereau, berbagai kesulitan itu bukan cuma mendera warga Atuka. “Di mana-mana, khususnya di Mimika pesisir, [situasinya] hampir sama. Saya tidak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan bagaimana dengan nasib kami punya anak-anak,” ujarnya.
Rentannya masyarakat adat
Dr Hanro Yonathan Lekitoo menjelaskan bahwa masyarakat adat Kamoro, termasuk masyarakat adat Sempan, merupakan bagian dari masyarakat adat yang hidupnya sebagai peramu atau pengumpul makanan (food gathering). Akibatnya, kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam, dan penghidupan mereka rentan terhadap perubahan alam sekecil apapun.
“Mereka punya kehidupan itu tidak membudidayakan entah ikan ataupun tumbuh-tumbuhan sebagai sumber pangan. Mereka tidak membudidayakan, namun hidup dengan mengambil apa yang disediakan oleh alam,” ujar Lekitoo.
Ketika lingkungan alamnya berubah, masyarakat adat akan mengalami dampak yang lebih signifikan dibandingkan masyarakat yang mengandalkan hidup dengan cara lain, seperti bercocok tanam atau berbudidaya. Itulah mengapa Lekitoo menyebut dampak aktivitas tambang PT Freeport Indonesia yang mengubah kondisi lingkungan dan alam di pesisir Kabupaten Mimika berdampak secara signifikan terhadap kehidupan maupun penghidupan masyarakat adat Kamoro, termasuk orang Sempan.
“Orang Kamoro 50 tahun lalu hidup dan sangat bergantung kepada alam. Tapi dengan adanya Freeport, sumber daya alam di situ terganggu karena tailing menghancurkan sejumlah kampung tempat hidupnya orang Kamoro. Sebut saja daerah Koperapoka, Nayaro, Ayuka, Tipuka dan Nawaripi. Sungainya habis tertutup [tailing], mereka punya sagu juga habis karena tertutup limbah tailing, mereka punya bakau habis. Hari ini mereka menjadi sangat susah,” kata Lekitoo.

Lekitoo menyatakan masyarakat adat memiliki siklus menjalani pola hidup yang disebut Kapiri. Kapiri adalah pola hidup di mana masyarakat meninggalkan tempat bermukimnya dengan memasuki hutan atau daerah aliran sungai, membangun bivak, dan hidup berminggu-minggu di hutan dan daerah aliran sungai untuk mencari makanan.
Masyarakat adat Kamoro menganut sistem ekonomi nafkah atau dikenal dengan subsistem . Dalam pola kehidupan itu, mereka sekedar mencari makanan untuk hari ini. “Jadi mereka mencari hari ini untuk hidup hari ini, dan besok dia cari lagi. Saudara-saudara kita orang Komoro mereka hanya dari sungai [membawa tangkapan ikan ke] pasar, balik lagi ke sungai, ke pasar. Pulang pergi di situ, dan mereka tidak mencari kekayaan di situ. Mereka hanya mencari kecukupan hidupnya setiap hari,” kata Lekitoo.
Ia juga menjelaskan bagaimana sungai menjadi urat nadi kehidupan masyarakat adat di pesisir Mimika. Pada September hingga Oktober 2016, Lekitoo bersama tim meneliti penggunaan Sungai Okoroppa oleh masyarakat adat Kamoro. Penelitian itu dibuat karena PT Freeport Indonesia berencana menutup Sungai Okoroppa.
Lekitoo menyatakan sekitar sebulan timnya memantau aktivitas masyarakat di Sungai Okoroppa sejak pukul 09.00 WP hingga pukul 14.00 WP. Mereka menghitung jumlah orang yang melintas di Sungai Okoroppa untuk mencari ikan, berdagang, mengujungi kerabat, bersekolah, hingga berobat.

“Kurang dari tiga minggu, hampir 1.000 orang lewat di sungai itu. Itu belum menghitung pengguna sungai di atas jam 14.00 WP sampai malam. Padahal banyak dari mereka menggunakan sungai pada saat malam, karena air pasang. Kadang mereka singgah di Kampung Amamapare di Pulau Karaka,” ujar Lekitoo.
Lekitoo menyatakan hasil penelitian itu kemudian dipresentasikan kepada manajemen PT Freeport Indonesia. “Masyarakat tidak mau [sungai itu] ditutup, karena itu akses satu-satunya orang Kamoro untuk masuk ke Pomako, terutama [bagi mereka yang datang] dari wilayah Mimika Timur Jauh,” ujarnya.
Masalahnya, demikian Lekitoo, hingga kini sudah ada setidaknya ada empat sungai yang ditutup karena terdampak pembuangan tailing PT Freeport Indonesia, yakni Sungai Amapiraripi, Amawuraro, Tawaiwo dan Yaimaima. Tailing PT Freeport Indonesia membuat masyarakat Kamoro kehilangan sumber pangan hidup untuk menokok sagu, ikan, kepiting hingga udang.
“Itu sumber pangan hidup mereka. Dan ketika itu sudah habis kita bisa lihat bahwa mereka betul-betul tidak punya sumber daya alam tempat ketergantungan hidup mereka. Kami berpikir, masa depan manusia Kamoro atau Mimika Wee ke depan akan seperti apa?” Lekitoo bertanya.

Lekitoo menyataan Sungai Okoroppa yang ditelitinya itu merupakan dapur, supermaket dan lumbung terakhir untuk masyarakat Kamoro. Jika Sungai Okoroppa ditutup, tindakan itu sama dengan menutup lumbung kehidupan masyarakat Kamoro.
“Sungai Okoroppa itu sebagai dapurnya, supermarketnya, lumbung pangan untuk masyarakat Kamoro. Jadi Okaroppa sungai terakhir di tutup maka sama dengan kitong tutup dapur, supermarket, tutup dia punya lumbung kehidupan. Kan empat sudah tutup, sisa yang terakhir yang menjadi harapan terakhir kemungkinan akan ditutup,” ujarnya.
Lekitoo menyatakan masalah tailing bukan hanya menutup sungai tapi sampai ke laut Arafura yang kini mengalami pendangkalan. Menurut Lekitoo ini bukan hanya persoalan di sungai-sungai untuk orang Kamoro tapi persoalan di laut Arafura untuk seluruh angkutan laut yang menggunakan daerah itu.
“Akhirnya saat kita dapat tempat yang dangkal itu motoris/penumpang kadang turun harus mendorong perahu supaya perahu itu bisa berjalan. Itu susah sekali kadang kita lihat masyarakat harus menunggu sampai betul-betul air naik baru speedboat atau perahu bisa keluar [dan melanjutkan perjalanan,” ujarnya.
Investasi sosial yang gagal?
PT Freeport Indonesia telah mengucurkan banyak bantuan bagi masyarakat adat yang terdampak aktivitas tambangnya. Dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau ANDAL bertajuk “Rencana Pengembangan dan Optimalisasi Tambang Tembaga dan Emas 300.000 Ton Biji/hari pada 2022”, PT Freeport Indonesia menyebutkan ratusan juta dolar telah disalurkan PTFI untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Dokumen itu menjelaskan PTFI memiliki investasi sosial pada 2021 dengan total 109,3 juta dolar atau Rp1,564 trilliun. Investasi sosial itu terbagi dalam bentuk Dana Kemitraan senilai 75,2 juta dolar atau Rp1,075 trillun, Dana Perwalian senilai 1,5 juta dolar atau Rp21,462 miliar.
Ada pula dana operasional Divisi Community Affair senilai 25,8 juta dolar atau Rp21,462 miliar. Juga berbagai pembiayaan proyek khusus senilai 2,4 juta dolar atau senilai Rp Rp34,339 miliar.
Dana investasi sosial juga digunakan untuk divisi lain PTFI sebesar 3,4 juta dolar atau senilai Rp48,647 miliar serta komite kontribusi PTFI sebesar 857,4 ribu dolar atau senilai Rp12,267 miliar.

Dana investasi sosial itu dijalankan untuk program sosial yang tersebar di seluruh area sekitar PTFI diantaranya di dataran tinggi meliputi Kampung Waa Banti, Kampung Aroanap dan Tsinga, dan di dataran rendah tersebar di Kampung Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Nayaro dan Koperapoka. Sejumlah kampung di pesisir meliputi Kampung Fanamo, Omawita dan Ohotya juga mendapat manfaat dari investasi sosial PT Freeport Indonesia.
Dokumen yang sama juga menyatakan PTFI dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) telah banyak memberikan kontribusi finansial bagi Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko).
PTFI sepanjang 2000 hingga 2019 memberikan kontribusi finansial kepada Lemasa sebesar 3 juta dolar AS. Sementara sepanjang 2003 hingga 2019 melalui YPMAK telah memberikan kontribusi sebesar 15,1 juta dolar. Pada Oktober 2020 PFTI kembali memberikan dukungan dana operasional sebesar Rp15 Miliar per tahun kepada Lemasa.
Sedangkan antara 2005 sampai 2019 PTFI juga telah memberikan kontribusi finansial kepada Lemasko sebesar 300 ribu dolar, dan sepanjang 2003 sampai 2019 YPMAK memberikan kontribusi finansial sebesar 17,4 juta dolar. Pada Oktober 2020 PTFI kembali memberikan dukungan dana operasional sebesar Rp15 Miliar pertahun bagi Lemasko.

Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih, Dr Hanro Yonathan Lekitoo menilai pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan PT Freeport Indonesia dan YPMAK tidak membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Kamoro. Hal itu terlihat dari tidak adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Kamoro.
“Masyarakat sepertinya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita bisa hitung berapa banyak orang Kamoro/Mimika Wee yang punya kemampuan ekonomi yang mumpuni di daerah Timika hari ini,” kata Lekitoo.
Menurut Lakitto harus ada rekayasa sosial, pendidikan, hingga ekonomi supaya masyarakat Kamoro bisa berpindah dari pola hidup meramu pindah ke pola hidup menetap, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan dampak perubahan lingkungan pesisir Mimika.
“Mereka tinggal dalam posisi seperti 50 tahun yang lalu. Jalan dari sungai ke pasar, kota, pasar kembali ke sungai. Dengan pola yang tidak berubah, dengan taraf hidup yang tidak beruah,” ujarnya.

Lekitoo menyatakan siklus dan pola kehidupan Kapiri—saat masyarakat adat meninggalkan permukiman untuk tinggal di bivak dan berburu berminggu-minggu di daerah aliran sungai atau hutan—membuat masyarakat adat Kamoro secara komunal dan tidak berorientasi untuk mengakumulasi modal. Jaring pengaman sosial mereka adalah kebersamaan dengan sesama, saling berbagi, dan saling menerima.
Akibatnya, mereka sulit bersaing dalam sistem perekonomian modern yang sangat individual. Di sisi lain, aktivitas tambang PT Freeport Indonesia memicu migrasi penduduk secara besar-besaran, mendatangkan warga dari berbagai penjuru Indonesia ke Timika yang kini menjadi pelaku utama perekonomian sektor formal dan non formal di Mimika.
“[Masyarakat adat hidup secara komunal, mencari hari ini untuk hidup hari ini. Itu sangat mempengaruhi [daya saing mereka] dalam sistem modern atau kapitalis. Banyak sekali pendatang yang datang ke situ dan kelompok pendatang ini mereka mengusai ekonomi di sana. [Sementara] orang Kamoro hanya dari pasar sungai jualan, balik lagi ke sungai pasar, jualan,” kata Lekitoo.
Lekitoo menyatakan tipologi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Papua seperti Kamoro tidak berpikir menimbun untuk mencari keuntungan. Masyarakat hidup dengan menjaga keseimbangan dengan alam tempat tinggalnya, dan dengan sesamanya. Akan tetapi, kearifan itu justru membuat mereka tersisih dalam sistem ekonomi modern yang individualis dan berorientasi mencari keuntungan dan mengakumulasi modal.

“Itu satu persoalan besar. Tapi kan bisa melalui rekayasa sosial, rekayasa pendidikan itu bisa diubah. Masa selama ini sekian puluh tahun tidak bisa merubah masyarakat yang hidupnya seperti itu dengan model pendidikan yang kita atur. Bisa di atur sehingga perubahan masyarakat yang tadi anak-anaknya ikut orangtuanya kita rubah supaya bisa diberdayakan,” katanya.
Lekitoo menyatakan perlu ada evaluasi pemberdayaan yang selama sekian puluh tahun dijalankan PT Freeport Indonesia dan YPMAK tidak berhasil membantu masyarakat adat Kamoro meninggalkan pola hidup berburu dan meramu. “YPMAK harus melakukan evaluasi itu. Misalnya hari ini baru satu orang Kamoro meraih gelar Doktor, yaitu [Leonardus Tumuka]. Kenapa uang sekian miliaran, mungkin trilunan, tapi untuk menciptakankan 30 sampai 100 doktor saja tidak bisa. Baru satu Doktor, Pak Leonardus Tumuka,” ujar Lekitoo mencontohkan.
Ia menekankan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan telah membuat masyarakat Kamoro maupun Sempan kehilangan kehidupan maupun penghidupan mereka. “Masyarakat mengalami situasi yang kritis ketika tailing [merusak] sumber daya alam masyarakat Kamoro itu mengalami degadrasi dan habis. Itu tanggungjawab dua lembaga besar yakni, Freeport lewat YPMAK, juga Pemerintah Kabupaten Mimika,” kata Lekitoo.

Kepala Seksi Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Maria Fransisca Mitapo mengakui tailing PT Freeport Indonesia ikut membuat pendangkalan sungai-sungai dan merusak ekosistem. Namun ia menyatakan belum ada temuan bahwa sedimen tailing itu mencemari biota air dan laut di pesisir Mimika.
“Kalau kita lihat secara kasat mata memang [terjadi] pendangkalan [sungai yang digunakan] untuk transportasi dan mata pencarian masyarakat pesisir. Yang di muaranya itu sendiri [sedimen tailing] yang paling halus, sisanya dialirkan ke Laut Arafura. Kalau secara kualitas ikan, belum ada ditemukan ikan yang tercemari tailing [atau] merusak kesehatan. Itu belum ada,” ujarnya.
Mitapo menyatakan selama PT Freepot Indonesia masih beroperasi tentu sulit untuk melakukan pemulihan sungai maupun ekosistemnya. Ia menyatakan pemulihan dapat dilakukan pasca operasional PT Freeport Indonesia.
“Ekosistem pasti terganggu karena ini lagi operasional. Nanti akan dipulihkan setelah pasca operasi itu. Kalau saat ini memang tidak bisa karena [masih] dalam proses operasional jadi kalau kerusakan itu pasti akan terjadi,” ujarnya.
Wakil Ketua II Lembaga Masyarakat Adat Kamoro atau Lemasko, Siprianus Operawiri mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia serius menangani masyarakat adat yang terdampak tailing PT Freeport Indonesia. Menurut Operawiri Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia terkesan tutup mata, padahal dampak tailing semakin besar.
“Mereka sudah tahu sebenarnya yang punya hak ulayat yang rusak itu siapa. Freeport dan pemerintah mereka tahu. Cobalah buka mata sedikit. Kunjungi sedikit di kampung mana yang dampak langsung, yang mana yang punya daerah rusak harus turun pantau langsung di titik-titik mana dampak langsung,” tutur Operawiri. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!