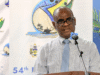Jayapura, Jubi – Yustina Kereway, perempuan 26 tahun ini selalu terlihat mendampingi ibunya, Esterlina Kereway, mengantarkan makanan dan minuman untuk tamu di Homestay Bwonbesayor. Bwonbesayor adalah satu dari sepuluh homestay yang bisa disewa oleh wisatawan di Kampung Aisandami, Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama.
Kegiatan ekowisata ini menjadi salah satu mata pencaharian warga Kampung Aisandami, terutama jika sasi diberlakukan di perairan sekitar kampung mereka. Karena pada umumnya, warga Kampung Aisandami menggantungkan hidup mereka pada hasil laut sekitar mereka.
Jika perempuan di Kampung Aisandami terlibat dalam kegiatan ekowisata, perempuan di Kampung Sombokoro, pergi ke laut untuk memancing dan menjual hasil laut itu, selain membuat kerajinan di rumah dan membuat kapur yang digunakan untuk menginang (makan pinang dan sirih).
More Read
Hidup bergotong-royong sesama perempuan menjadi kunci di Sombokoro. Saling membantu mereka lakukan terutama di tengah keterbatasan, seperti ketiadaan perahu dan mesinnya yang menjadi alat utama untuk berangkat ke laut mencari ikan atau teripang.
Setiap kali bepergian ke pasar terdekat seperti pusat distrik di Windesi yang berjarak 13 km naik perahu atau pusat distrik tetangga di Wasior yang berjarak 37 km untuk menjual hasil laut, para perempuan di Kampung Sombokoro harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli bensin, sekitar 10 hingga 20 liter sekali jalan dengan mesin 15 PK.
Perempuan aktor utama menjaga kearifan lokal
Peran perempuan di Kampung Sombokoro tidak berhenti pada aktivitas mencari ikan atau teripang. Saat upacara tutup sasi, mereka juga mengambil peran di belakang layar.
“Kalau laki-laki itu fokus pada upacara sasi, perempuan membuat makanan daerah, kolak, jagung, petatas, keladi, dan buah merah,” kata Tovelina Bebari, seorang ibu di Kampung Sombokoro.

Para perempuan juga aktif membuat kerajinan tangan seperti noken dari tali genemo, keranjang bambu, dan hiasan dari kerang. Hasil kerajinan itu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka saat sasi diberlakukan di perairan Sombokoro. Namun jika pasar hasil kerajinan tersebut sedang sepi, perempuan Sombokoro memilih fokus ke laut untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti Tovelina yang harus membiaya anak-anaknya yang kini bersekolah di SMA.
“Karena tidak semua wilayah perairan diberlakukan sasi,” kata Tovelina.
Masyarakat Teluk Wondama menyadari kekayaan ekosistem laut Teluk Wondama yang merupakan perpaduan mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah karunia, sekaligus tanggung jawab
Perempuan Kampung Sombokoro lainnya, Marlin Rumbarar setiap hari bekerja mengumpulkan kulit bia (kerang) yang terdampar di pesisir pantai. Kerang itu ia bakar menjadi kapur sirih. Kapur putih itu kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya.
“Kita bikin kapur itu untuk anak-anak sekolah,” ujar Marlin.
Pekerjaannya dimulai dari memungut kulit bia di pantai, membersihkannya, dan menjemurnya hingga kering. Setelah itu, kulit bia dibakar menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan dari pantai.
“Kalau kayu bakar banyak, bisa dapat sepuluh jerigen kapur,” katanya.
Jika kayu bakar banyak, ia bisa mendapatkan kapur sirih sebanyak 10 jerigen 5 liter. Namun jika kayu bakar yang ia dapatkan sedikit, hasilnya hanya sekitar lima jerigen. Membuat kapur sirih ini bukan menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi Marlin. Selain membuat kapur sirih, ia juga mencari teripang dan membuat ikan asin. Semua usaha itu ia lakukan sendiri demi membiayai sekolah anak laki-lakinya di SMA, terutama saat sasi diberlakukan disekitar perairan Sombokoro.
Cerita Nurhalimah
Perempuan lain di Sombokoro, Nurhalimah Mnuari yang usianya tak lagi muda dengan rambut yang memutih, namun semangatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak pernah padam. Ia juga dikenal sebagai perempuan pembuat kapur sirih dari kulit kerang (bia) kering. Nurhalimah juga kerap mencari dan mengumpulkan berbagai jenis kerang seperti kima, bia kodok, dan bia jari-jari di pantai saat air surut.
“Saya bikin kapur sirih ini untuk menambah pendapatan biaya anak sekolah di Wasior. Lumayan bisa dapat untung sekitar Rp1 juta,” katanya lirih.
Dulu, sebelum ada sasi, ia bersama ibu dan neneknya kerap memancing saat air laut surut. Dengan karung noken yang dijahit sendiri, mereka menangkap ikan bobara dan ikan-ikan kecil lainnya. Menurutnya, saat itu ia hanya mengikuti cara orang tuanya menangkap ikan, tidak perlu mata kail dan tidak perlu pergi jauh ke tengah laut.

Kini, di usianya yang renta, Nurhalimah merasa semakin sulit mencari ikan. Ia mengakui sejak tahun 2007 tangkapan ikan semakin berkurang. Berbeda dengan masa kecilnya dulu, sekarang mencari ikan sangat berbeda, harus pakai mata kail dan menggunakan perahu.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia tidak hanya memancing, tetapi juga menyulam taplak meja dan membuat garam sendiri. Ia bisa menghasilkan lima kilo garam dalam dua hari dengan memanaskan air laut.
Nurhalimah punya anak 14 orang. Ia bersyukur anak-anaknya sudah bersekolah semua. Bahkan ada yang bersekolah di Jawa.
Tentang sasi yang diterapkan di kampungnya, Nurhalimah mengakui ia tidak dapat apa-apa dari sasi. Karena ia hanya berkebun saja. Namun ia mendukung pemberlakuan sasi di perairan Sombokoro, karena ia sendiri merasakan perbedaan dalam mencari hasil laut saat masa kecilnya dan sekarang.
Jika kampungnya melakukan sasi, ia melakukan apa saja untuk membantu. Ia yakin dengan menjaga cara hidup tradisional dan semangat bergotong royong seperti sasi adalah warisan yang harus tetap hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka.
“Ini mengajarkan anak cucu kami menghargai dan merawat laut dengan segala isinya,” katanya.
Pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang tidak merusak
Di Kampung Yop Meos, ibu-ibu di kampung ini tahu kapan harus pergi menangkap ikan. Mereka menangkap ikan saat air laut surut di tempat tertentu dengan alat sederhana. Itu bentuk pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang tidak merusak. Mereka sadar jika laut dieksploitasi secara berlebihan atau tercemar, ikan-ikan itu bisa hilang. Menjaga laut berarti memastikan keberadaan ekosistem terumbu karang, tempat ikan berkembang biak.
“Saat air laut surut, kami berperahu atau menggunakan sampan ke salah satu tempat yang disebut Ujung Tanjung. Di tempat ini tidak diberlakukan sasi seperti tempat lainnya. Di lokasi itu kami bisa mendapatkan ikan karang yang banyak. Ada jenis ikan kerapu, ikan kakap dan jenis ikan karang lainnya,” kata Ibu Ayomi, warga kampung Yop Meos.
Karena laut, kata Ibu Ayomi bukan hanya ruang geografis, tapi ruang hidup—sumber pangan dan penghidupan harian. Ikan-ikan karang yang ditangkap bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari rantai kehidupan keluarga, dapur, dan masa depan anak-anak. Menjaga laut berarti menjaga keberlangsungan hidup komunitas pesisir seperti Yop Meos.

Meskipun secara historis, di Papua wilayah sasi dikelola oleh laki-laki namun perempuan di kampung-kampung pesisir di Teluk Wondama, seperti di Aisandami, Sombokoro Yop Meos dan Menarbu menjadi aktor utama dalam menjaga kearifan lokal dan mendukung ekonomi keluarga terutama sejak sasi mulai diberlakukan. Mereka berperan penting sebagai garda depan di balik upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi di sana. Organisasi-organisasi non pemerintah sering melakukan penguatan konservasi berbasis masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pelaku utama di wilayah pesisir Teluk Cenderawasih.
Kearifan perempuan juga menjadi benteng terakhir bagi laut, mangrove, dan ikan-ikan yang kian terancam oleh ‘ketamakan pasar’. Aturan adat yang dijalankan kadang lebih dituruti daripada aturan pemerintah. Dan kaum perempuanlah yang lebih konsisten menjalankan aturan adat ini.
Peran perempuan di Kampung Sombokoro tidak berhenti pada aktivitas mencari ikan atau teripang. Saat upacara tutup sasi, mereka juga mengambil peran di belakang layar.
Dalam praktik konservasi adat di Teluk Wondama perempuan memegang peran penting, meski tidak selalu terlihat. Walaupun dalam struktur sosial yang patrilineal, keputusan formal biasanya diambil oleh laki-laki, namun bisikan perempuan sangat menentukan arah keputusan itu. Perempuan memang tidak tampil di rapat adat, tapi mereka berbisik ke suami atau kepala marga. Mereka tahu wilayah mana yang penting untuk pangan, mana yang boleh ditutup, mana yang jangan disentuh. Jadi para perempuan ini sebenarnya penentu.
Aksamina Betay mencontohkan ketika sasi diberlakukan di Menarbu, laki-laki sepakat untuk menutup seluruh kawasan, namun para perempuan mengingatkan bahwa ada wilayah pesisir yang menjadi tempat mencari makan mereka sehari-hari. Akhirnya, yang ditutup hanya wilayah tubir laut yang jauh, sementara pesisir tetap bisa dimanfaatkan oleh mama-mama untuk mengambil kerang atau mencari ikan kecil.
“Suara kami memang tidak terdengar di depan, tapi keputusan kami hadir pada hasil akhir,” ujar Aksamina.
Namun Aksamina mengatakan ada beberapa tempat yang kuat aturan patrilinealnya. Ia mencontohkan di Kampung Menarbu tempatnya tinggal, hanya laki-laki yang boleh menangkap ikan julung dan itu pun dengan alat tangkap sederhana. Tidak boleh ada yang tahu lokasi persisnya selain pemilik tempat ikan julung biasa berada.
Pada banyak kampung di Teluk Wondama, kata Aksamina, masyarakat mengenal konsep wilayah pamali, yaitu kawasan sakral yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh warga lokal, apalagi orang luar.
Di sanalah tabungan ekosistem dijaga, tempat terumbu karang tumbuh utuh, lamun berkembang lebat, dan mangrove menebalkan akar penyangga daratan.
“Wilayah pamali itu bisa di dusun, RT, atau bahkan hanya sepetak kebun. Ada tempat yang diberi tanda dengan kain merah, kadang disumpah agar tidak diambil pinangnya, kelapanya, bahkan ikannya. Itu cara masyarakat menjaga tabungan hidupnya,” katanya.

Sasi, kata Esterlina Kereway memang menjadi semacam sistem ekonomi berbasis ekologi. Hasil laut tidak diambil sembarangan, melainkan hanya saat dibutuhkan. Ketika anak hendak masuk sekolah, ibunya akan membuka wilayah sasi untuk panen teripang. Ketika gereja butuh dana, barulah kampung membuka laut agar bisa menangkap ikan bubara.
“Ini seperti tabungan, mereka jaga dulu, baru buka kalau perlu. Jadi bukan budi daya pakai keramba atau pakan buatan. Ini budi daya alami yang selaras dengan alam,” ujar Esterlina.
Model ini dikenal dengan istilah budi daya semi-alami. Budi daya ini terbukti lebih cocok bagi masyarakat pesisir Papua yang masih sangat bergantung pada alam dan memiliki hubungan spiritual dengan wilayahnya. Namun memadukan dengan program modern memiliki tantangan tersendiri. Program budi daya modern kerap gagal karena tidak sejalan dengan kultur lokal.
Di sisi lain, ketika praktik konservasi adat seperti sasi berjalan, masalah muncul dari luar, yaitu tidak adanya sistem pasar tetap, distribusi logistik, bahkan penguatan kelembagaan seperti BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) yang macet. Misalnya dulu ada yang mencoba bangun bagan untuk menangkap ikan. Ada 21 bagan, tapi pasarnya tidak ada, es susah. Mau jual ke Nabire belum tentu laku. Jadi masyarakat kembali ke cara lama.
Bahkan ketika hasil tangkapan melimpah, tidak ada jaminan akan terjual dengan harga layak karena minimnya infrastruktur dan manajemen.
Masyarakat Teluk Wondama menyadari kekayaan ekosistem laut Teluk Wondama yang merupakan perpaduan mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah karunia, sekaligus tanggung jawab. Ketiganya saling mendukung untuk menjaga keberlanjutan. Mangrove menyaring lumpur, lamun menjaga kesuburan, dan terumbu karang menyediakan habitat.
Peran perempuan sangat signifikan
Peran perempuan ini juga diakui Nurhani Widiastuti, peneliti dan dosen Universitas Papua (Unipa). Berdasarkan penelitiannya, Nurhani menyimpulkan, peran perempuan sangat signifikan dalam pengelolaan ekosistem pesisir di Teluk Wondama.
Menurut Nurhani perempuan di kampung-kampung pesisir, seperti Menarbu dan Sombokoro, menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Perempuan, menurutnya bukan hanya pengguna utama sumber daya laut, tetapi juga penjaga nilai-nilai keberlanjutan.

Ia mengakui bahwa dalam praktik sasi, perempuan berperan penting, meski tidak secara formal masuk dalam struktur pengelola. Mereka memberi masukan kepada para lelaki yang menjadi pengambil keputusan, terutama ketika akses perempuan terhadap hasil laut terhambat oleh kebijakan sasi yang terlalu ketat.
“Saya menemukan ketika perempuan tidak bisa mengakses sumber daya seperti kima, bia kodok, atau siput mangrove, itu berdampak langsung kepada kesejahteraan keluarga. Akhirnya, perempuan angkat suara dan memengaruhi kebijakan agar ada zona yang tetap terbuka bagi mereka,” katanya.
Kesadaran perempuan untuk menjaga sumber daya laut, kata Aksamina, juga terbangun dari nilai-nilai kasih sayang. Para perempuan di Teluk Wondama sering berkata mereka sudah sayang ikan-ikan itu seperti anak-anak mereka. Jadi, saat buka sasi pun para perempuan ini tidak banyak menangkap ikan. Mereka hanya menangkap lobster dan teripang saja.
Namun, Nurhani menyoroti potensi marginalisasi perempuan ketika skema perdagangan karbon dan konservasi tidak dikelola secara inklusif.
“Perempuan yang paling rentan ketika ada land grabbing [perampasan lahan]. Mereka yang biasa memanfaatkan mangrove dan lamun justru bisa tersingkir,” katanya.
Nurhani mengingatkan pentingnya gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender dalam kebijakan kelautan dan konservasi di Teluk Wondama. Perempuan di kampung pesisir, lanjutnya, punya nilai-nilai inklusif dan kepedulian yang luar biasa. Kalau kita bicara people, planet, dan profit, perempuan harus ada di dalamnya.
“Dengan demikian, tambahnya, suara perempuan bukan hanya soal ekonomi rumah tangga, tapi juga kunci keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem pesisir di Teluk Wondama,” kata Nurhani. (*)
English version
Tim Liputan
Reporters : Dominggus A Mampioper, Alberth Yomo, Adlu Raharusun, Alfian Putra Abdi
Photographer : Engelberth Wally
Videographers : Yuliana Lantipo, Anggi Sagita
Narator : Natalia Andilan
Video Editor : Maurids Yansip
Infographic : Leonard Ohee
Editors : Victor Mambor, Aryo Wisanggeni, Syofiardi Bachyul
Translators : Nuevaterra Mambor, Dina Danomira, Elfriede Rumaseuw