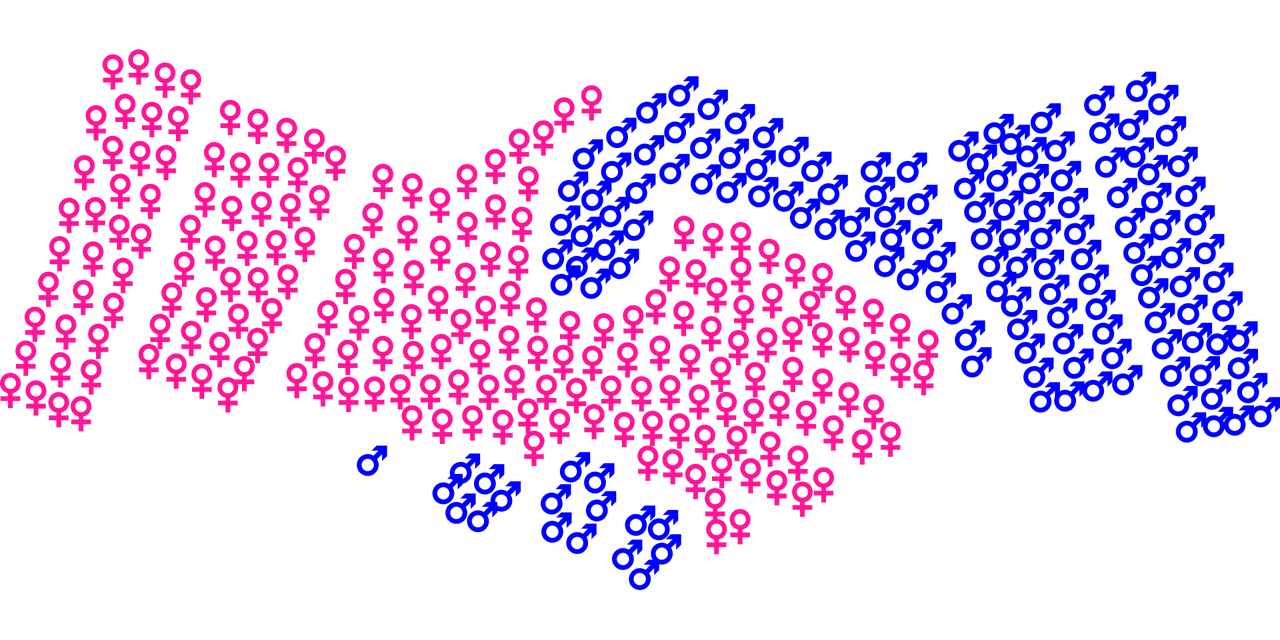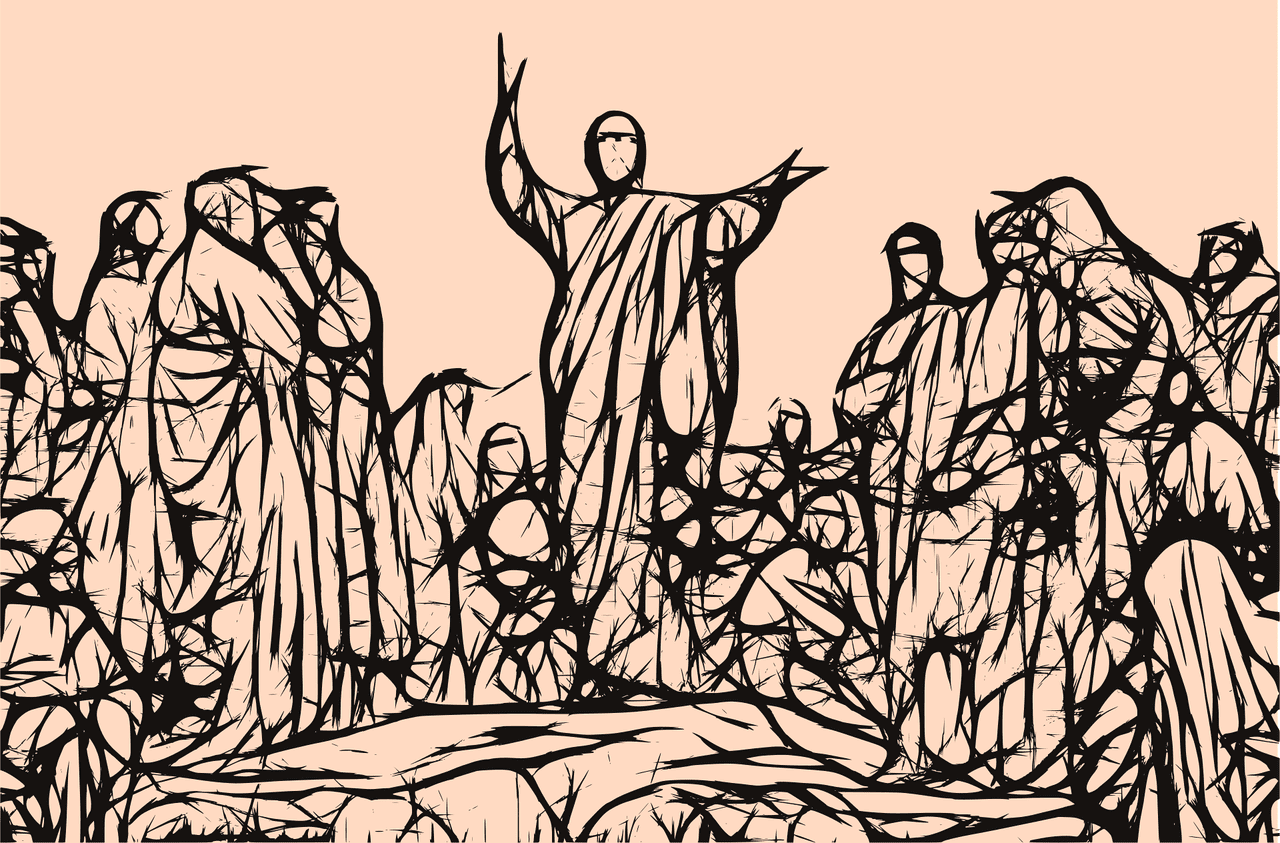Oleh: Siorus Degei
Ada satu fenomena hukum yang sangat memukul sense of nation kita di Papua, yaitu proses implementasi hukum bagi rakyat Papua. Bukan mitos lagi bahwa hukum di Papua itu nihil berpihak pada rakyat dan imun bagi penguasa, serta pengusaha “bejat”.
Bukan pula tanpa alasan bila kita berargumentasi bahwa hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mati suri, bahkan mati total perihal implementasinya bagi rakyat Papua yang menuntut kebenaran, keadilan dan kedamaian.
Beberapa contoh konkret bisa kita terawang bersama. Bahwa memang hukum NKRI itu “mati suri” di Papua.
Fenomena-fenomena “kematian” hukum NKRI di Papua dapat dilihat dalam contoh kasus berikut ini:
Pertama, kasus pembunuhan tiga tokoh kharismatik Papua; Arnold Clemens Ap (budayawan, antropolog, dan musisi Papua Barat) pada 1984, Dr. Thomas Wainggai (cendekiawan, pimpinan politik, budayawan, filsuf, dan nasionalis) pada 1996, Dortheys Hiyo Eluay (mantan ketua Presidium Dewan Papua) pada 2001.
Tiga tokoh ini jelas-jelas terbukti dieksekusi mati secara sadis oleh pihak aparat negara, tetapi hingga hari ini proses persidangannya masih “ngambang”. Lebih ironis dan tragisnya lagi para pelaku penculikan dan pembunuhan ketiga tokoh tersebut mendapatkan kenaikan pangkat;
Kedua, kasus penangkapan dan penahanan juru bicara Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo. Proses kriminalisasi terhadap Victor Yeimo ini terbilang sangat “cacat hukum, moral, dan HAM”.
Victor yang sebenarnya korban perlakuan rasisme pada 16 Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban peradilan rasisme pula di Papua. Sebelum Victor ditangkap, ada tujuh pejuang anti rasisme yang menjalani proses hukum dan peradilan di pengadilan tinggi Kalimantan Timur, dan dengan begitu kasus rasisme sudah final, walau ada banyak kejanggalan (tirto.id, 18/6/2020).
Karenanya, kebanyakan pihak menyatakan bahwa kriminalisasi hukum terhadap Victor Yeimo ini murni masalah baru, praktik kapitalisme dan monopolisme hukum, kriminalisasi aktivis HAM Papua, dan bercokol muatan politis (status politik Papua).
Bahwa ia ditahan berdasarkan akumulasi perjuangannya dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian di Papua;
Ketiga, kasus penangkapan delapan mahasiswa pengibar Bintang Fajar, Rabu (1/12/2021) di depan Gedung Olahraga Cenderawasih, Kota Jayapura. Delapan mahasiswa Papua ini dengan tipikal penuh demokratis, pancasilais, dan humanis melakukan long march dan mengibarkan Bintang Fajar, membawa baliho Bintang Fajar dan pamflet bertuliskan “Self Determination for West Papua, Welcoming UN High Commissioner for Human Right to West Papua, Stop Militerisme in West Papua.”
Delapan mahasiswa itu adalah Malvin Yobee (29), Melvin Fernando Waine (25), Devion Tekege (23), Ernesto Matuan (19), Zode Hilapok (27), Maksimus Simon Petrus Youw (18), Ambrosius Fransiskus Elopere (21), dan Lukas Kitok Uropmabin, 21 tahun (Jubi.co.id, 1/12/2020).
Pada artikel ini penulis lebih fokus pada isu ketiga, yakni penangkapan delapan mahasiswa Papua pada 1 Desember 2021. Terutama pembahasan akan lebih berkutat pada proses persidangannya.
Seperti disentil di muka bahwa pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2021 itu sarat kapitalisasi, manipulasi dan kriminalisasi hukum dan moral, khususnya pasal makar.
Hemat penulis ada beberapa kejanggalan yang dilakukan aparat polisi, hakim, jaksa, dan jurnalis intelijen. Hal ini ditandai dengan beberapa hal aneh bin ajaib.
Pertama, Kapolda Papua, Mathius D. Fakhiri, dan jajarannya gagal, sebab mereka lalai menetralisir nuansa tanggal 1 Desember seperti biasanya, karena peristiwa itu terjadi di dekat markas Polda Papua, sehingga dari sinilah terlihat jelas spesialisasi dan profesionalisme Kapolda Papua, dan jajarannya yang “tidak becus”.
Kedua, Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa juga “gagal” dalam rangka mencari resolusi konflik di Papua, sebab beliau tidak disambut oleh antusiasme masyarakat Papua. Sebaliknya beliau disambut oleh aksi pengibaran Bintang Fajar oleh 8 mahasiswa Papua sebagai representasi masa depan Papua dan delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Menurut Malvin Yobee, koordinator tim aksi, mereka melakukan aksi itu murni mewakili ULMWP atau representasi seluruh bangsa Papua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jenderal Andika Prakasa telah “gagal total” menjalankan tugasnya (Fajarpapua.com, 1/12/2021).
Ketiga, jurnalis NKRI tidak profesional dan buta hukum, sebab delapan mahasiswa itu ditulis sebagai pemuda. Dan baliho menyerupai bendera Bintang Fajar itu mereka sebut sebagai benar-benar bendera Bintang Fajar, padahal sudah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang Bendera Kebangsaan.
Berdasarkan aturan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009, bendera Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dua pertiga dari panjang, sedangkan bendera Bintang Kejora itu terdiri dari sebuah pita vertikal merah di sepanjang sisi tiang, dengan bintang putih berujung lima tengahnya. Di kanannya terdapat tujuh garis biru, yang melambangkan tujuh wilayah adat.
Asap dan bara api
Sebenarnya delapan mahasiswa hanya mengibarkan kain besar yang kebetulan dibuat dengan motif bendera Bintang Kejora. Jadi tidak perlulah melabeli pengibaran bintang Kejora itu dengan makar dan tapol.
Sekali lagi, itu bukan peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora resmi dan dengan begitu Papua langsung merdeka, melainkan hanya pengibaran Bintang Kejora.
Keempat, Pemerintah Indonesia melalui Jenderal Andika Prakasa, Kapolda Papua, Mathius Fakhiri, Hakim dan Jaksa telah “gagal total” menjalankan tugas pokoknya dalam menyikapi peristiwa pengibaran bintang fajar pada 1 Desember 2021 itu. Sebelum ada pelurusan sejarah tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua atau tidak dengan mekanisme peradilan internasional melalui Mahkamah Konstitusi Internasional mereka sudah mengklaim dan melegitimasi bahwa peristiwa pengibaran bintang fajar itu adalah tindakan makar.
Hal ini pula yang ditegaskan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay. Bahwa pemerintah tidak perlu bersusah payah mengipas asap, tetapi membenahi tungku dan mematikan baranya atau masalahnya (Papua.tribunnews.com, 4/12/2021).
Mengkriminalisasi delapan mahasiswa itu dengan pasal makar dan tuduhan tapol, sebenarnya mau menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia mendorong dan mengamini deklarasi dan proklamasi tanggal 1 Desember hari kemerdekaan bangsa dan negara West Papua secara defacto dan dejure.
Jika rezim ini masih “sehat akal budi dan murni hati nuraninya” pasti mereka akan pertama-tama meluruskan dulu sejarah status politik Papua dalam bingkai NKRI, apakah memang benar legal standing bangsa Papua itu sudah sah dan final secara mekanisme hukum internasional (PBB, Mahkamah Konstitusi Internasional) atau belum final, manipulatif dan cacat?
Jakarta harus ingat bahwa ada amanah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komnas HAM dan Pengadilan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Bab XII Pasal 45 dan 46 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2001.
Namun, sekali lagi, konflik Papua harus diselesaikan dengan, dalam dan melalui mekanisme PBB. Bahwa persoalan aneksasi 1962, Pepera 1969 dan rentetan pelanggaran HAM sejak 1960-an itu harus dibahas atau dikupas tuntas. Biar jelas di hadapan komunitas internasional melalui Mahkamah Konstitusi Internasional dan Pengadilan HAM internasional di bawah monitoring PBB.
Bebaskan tapol Papua dan segera gelar dialog
Lebih baik Jakarta tidak pusing tujuh untuk mengipas asap konflik berkepanjangan di Papua dengan menangkap dan menahan aktivis HAM Papua dengan jurus kriminalisasi hukum, pasal makar, stigma diskriminatif, label tapol dan lainnya sebagainya.
Sudah saatnya kedelapan mahasiswa pengibar bintang fajar, Victor Yeimo dan semua tapol Papua itu dibebaskan tanpa syarat. Langkah alternatif yang bisa disiasati oleh Pemerintah Pusat dan orang Papua untuk membenahi “tungku” dan mematikan “bara api” konflik Papua adalah, dengan membuka lebar-lebar ruang demokrasi melalui dialog damai.
Almarhum Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai (mantan koordinator Jaringan Damai Papua atau JDP) melalui bukunya “Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua” (2009) telah menggagas dialog damai yang dimaksudkan tersebut. Juga peneliti senior LIPI/BRIN, mendiang Dr. Muridan Widjojo dalam “Papua Improving the Present, and Securing the Future” (2009).
Dua buku di atas bisa menjadi “peta jalan” bagi Jakarta dan Papua untuk menciptakan “Papua Tanah Damai”. Pemerintah pusat bisa mendekati JDP, dan LIPI untuk merealisasikan cita-cita Papua tanah damai dan Papua baru melalui dialog Jakarta – Papua. (*)
Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura-Papua